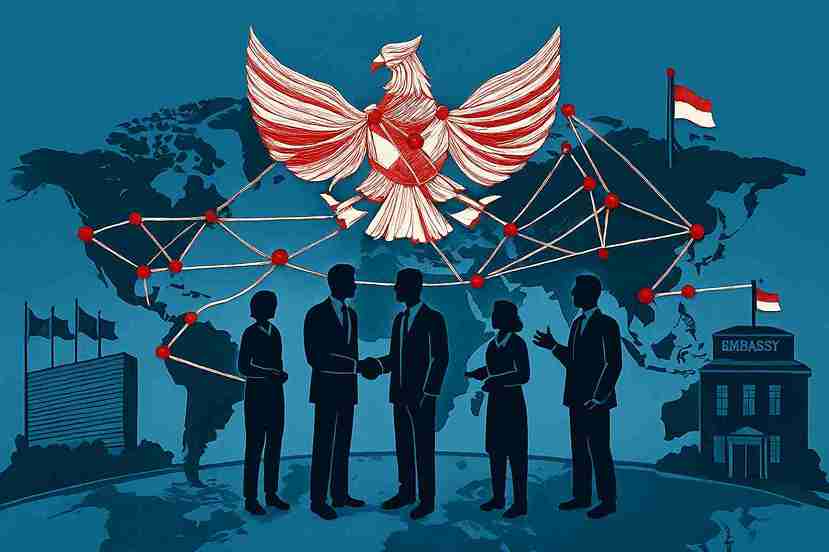Ketika kebenaran ditukar dengan kekuasaan, maka sejarah tidak lagi hanya menjadi catatan peristiwa, tetapi juga berubah menjadi cermin dari tragedi kemanusiaan yang terus berulang. Kebenaran yang sejatinya bersifat universal, murni, dan luhur, dikorbankan di altar kepentingan sempit demi mempertahankan kursi, pengaruh, dan dominasi. Proses ini bukan sekadar pengkhianatan pada nilai moral, melainkan juga penyelewengan hakikat eksistensi manusia yang seharusnya mencari dan menegakkan kebenaran.
Dari zaman kuno hingga dunia modern, kita melihat pola yang sama: mereka yang berkuasa seringkali tergoda untuk mengaburkan kebenaran, memanipulasi realitas, bahkan menukar nurani demi menjaga singgasana kekuasaan yang fana. Namun, dari setiap pengkhianatan itu selalu lahir suara-suara perlawanan, tokoh-tokoh yang menolak tunduk, dan kesaksian yang abadi bahwa kebenaran meskipun ditukar dengan kekuasaan, tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah.
Dalam tradisi keagamaan dan filsafat, persoalan ini telah lama diperbincangkan. Di Yunani Kuno, Socrates adalah salah satu tokoh yang dengan tegas menolak kompromi antara kebenaran dengan kepentingan politik. Ia lebih memilih meminum racun hemlock daripada meninggalkan prinsip mencari kebenaran dan menyebarkannya kepada masyarakat Athena. Dalam pengadilannya, Socrates dituduh merusak moralitas kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa, padahal tuduhan itu hanyalah strategi penguasa untuk membungkam suara kritis yang mengancam stabilitas kekuasaan mereka.
Socrates menjadi simbol bahwa kebenaran tak boleh ditukar dengan keselamatan diri atau kemudahan politik. Ia mengorbankan nyawanya untuk menegaskan bahwa kekuasaan tanpa kebenaran hanyalah ilusi yang rapuh. Tetapi sebaliknya, mereka yang menukar kebenaran dengan kekuasaan menjadikan pengadilan itu sebagai panggung legitimasi, menunjukkan bagaimana sistem hukum bisa dijadikan alat pelestarian dominasi.
Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam sejarah Eropa abad pertengahan, ketika institusi gereja yang seharusnya menjaga nilai-nilai kebenaran transendental justru jatuh dalam godaan kekuasaan duniawi. Praktik indulgensi, di mana dosa dapat ditebus dengan uang, adalah bentuk konkret bagaimana kebenaran iman ditukar dengan kepentingan ekonomi dan politik. Martin Luther kemudian bangkit melawan dengan gerakan Reformasi, memakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, menyingkap korupsi teologis yang telah mengakar.
Perlawanan ini mengguncang fondasi kekuasaan Gereja Katolik Roma dan membuka jalan bagi lahirnya Protestanisme. Di sini, Martin Luther mewakili suara kebenaran yang menolak ditukar, sementara para pemimpin gereja kala itu mencerminkan wajah kekuasaan yang mengkhianati amanah spiritual demi mengokohkan dominasi sosial-politik mereka. Dengan keberanian Luther, sejarah membuktikan bahwa menukar kebenaran dengan kekuasaan hanya akan menimbulkan krisis legitimasi yang pada akhirnya meruntuhkan fondasi kekuasaan itu sendiri.
Dalam ranah politik modern, kita juga menemukan contoh bagaimana kebenaran dikorbankan di hadapan ambisi kekuasaan. Niccolò Machiavelli dalam karya terkenalnya Il Principe menjelaskan secara gamblang bahwa demi menjaga kekuasaan, seorang penguasa boleh menggunakan segala cara, termasuk manipulasi, penipuan, dan kekerasan. Meski karya ini sering ditafsirkan sebagai realisme politik yang jujur, ia juga membuka mata kita pada kenyataan pahit bahwa kebenaran moral sering kali tidak sejalan dengan logika kekuasaan.
Banyak diktator modern yang menjadikan Machiavelli sebagai inspirasi, dari Mussolini hingga Hitler. Adolf Hitler, misalnya, membangun kekuasaan Nazi dengan propaganda kebohongan yang sistematis. Ia meyakinkan bangsa Jerman bahwa kaum Yahudi adalah penyebab seluruh krisis mereka, padahal itu hanyalah rekayasa untuk menyatukan massa di bawah ideologi fasis. Dalam hal ini, kebenaran sejarah, kebenaran sosiologis, bahkan kebenaran moral dikorbankan demi ambisi seorang tiran. Dunia akhirnya menyaksikan konsekuensi tragis dari ketika kebenaran ditukar dengan kekuasaan: perang dunia, genosida, dan kehancuran peradaban.
Fenomena menukar kebenaran dengan kekuasaan juga terjadi dalam politik kontemporer yang sarat dengan hoaks, disinformasi, dan propaganda digital. Kekuasaan di era modern sering dipertahankan bukan dengan senjata, tetapi dengan manipulasi opini publik. Kebenaran dikaburkan melalui algoritma, narasi dipelintir demi kepentingan elite, dan fakta ditenggelamkan oleh lautan kebohongan yang viral.
Tokoh-tokoh oposisi di berbagai negara yang mencoba menyuarakan kebenaran seringkali dikriminalisasi, dipenjara, atau bahkan dihilangkan. Namun pola ini menunjukkan ironi yang sama: ketika kekuasaan merasa perlu menukar kebenaran dengan kebohongan, sesungguhnya ia telah menunjukkan rapuhnya legitimasinya. Kekuasaan yang berdiri di atas kebohongan ibarat istana pasir yang sewaktu-waktu bisa dihantam gelombang.
Ketika kebenaran ditukar dengan kekuasaan, yang terjadi adalah distorsi terhadap realitas dan pengkhianatan terhadap martabat manusia. Kekuasaan memang bisa bertahan untuk sementara waktu dengan kebohongan, tetapi kebenaran memiliki sifat yang tidak bisa dimusnahkan. Ia mungkin ditekan, disembunyikan, atau diputarbalikkan, namun lambat laun ia akan kembali menyeruak, menghantam fondasi kekuasaan yang rapuh. Sejarah adalah bukti nyata bahwa setiap penguasa yang menukar kebenaran dengan kekuasaan pada akhirnya tumbang, sementara mereka yang mempertahankan kebenaran meski kehilangan segalanya justru diabadikan sebagai teladan.