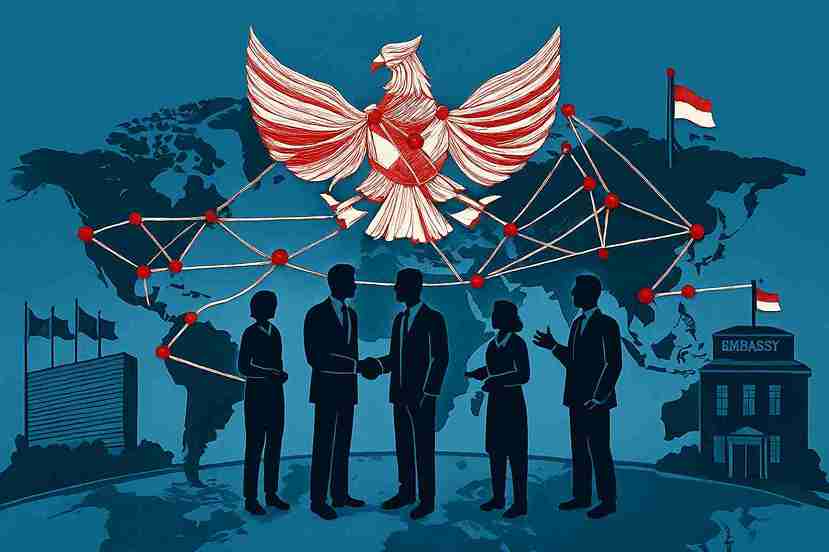Penetapan darurat militer di Indonesia merupakan isu yang sarat dengan kompleksitas, baik dari aspek hukum, politik, sosial, maupun kemanusiaan. Secara normatif, darurat militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan suatu wilayah atau bahkan seluruh Indonesia dalam keadaan darurat, baik darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang.
Instrumen hukum ini lahir dalam konteks politik yang sarat ketegangan pada masa awal Orde Lama, ketika stabilitas negara menghadapi ancaman dari berbagai pemberontakan daerah, ketidakpastian politik, serta ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Namun, dalam konteks demokrasi kontemporer, penggunaan mekanisme darurat militer sering dianggap berpotensi menghadirkan bahaya serius bagi kelangsungan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlangsungan tata kelola negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menimbulkan perdebatan mendasar mengenai urgensi, proporsionalitas, serta legitimasi dari penetapan keadaan darurat militer.
Bahaya utama dari penetapan darurat militer terletak pada konsentrasi kekuasaan yang sangat besar di tangan eksekutif dan militer. Ketika darurat militer diberlakukan, fungsi sipil praktis dapat diambil alih oleh komando militer. Hal ini berarti lembaga-lembaga sipil yang selama ini berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, seperti parlemen, lembaga yudikatif, maupun lembaga independen lain, berpotensi dilemahkan atau bahkan disingkirkan. Kondisi semacam ini membuka jalan bagi terjadinya praktik otoritarianisme, di mana kebebasan sipil dapat dibatasi secara masif tanpa mekanisme kontrol yang memadai.
Selain konsentrasi kekuasaan, bahaya lainnya muncul dari potensi pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat militer, aparat keamanan memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melakukan tindakan-tindakan represif, mulai dari penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, penyensoran media, hingga tindakan kekerasan yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pengalaman Indonesia di Aceh sebelum era perdamaian Helsinki, maupun di Timor Timur sebelum kemerdekaan, memperlihatkan bahwa penerapan status darurat militer sering diikuti oleh peningkatan jumlah pelanggaran HAM. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat sipil ketika berada di bawah kendali militer, terutama kelompok rentan seperti aktivis, jurnalis, dan masyarakat adat yang kerap dijadikan target represi. Bahaya tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena dapat menimbulkan trauma sosial yang berkepanjangan serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dari sisi politik, penetapan darurat militer dapat mengganggu keseimbangan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia pascareformasi. Sistem politik yang berdasarkan prinsip checks and balances berpotensi lumpuh ketika semua keputusan penting diambil secara terpusat oleh struktur militer. Hal ini tidak hanya merusak legitimasi demokratis, tetapi juga dapat menciptakan preseden buruk bagi masa depan politik Indonesia. Jika darurat militer digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik politik atau perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat, maka hal ini akan menormalisasi penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi persoalan sipil. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, di mana konflik politik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme deliberasi, pemilu, dan lembaga peradilan, bukan melalui represi bersenjata.
Implikasi dari darurat militer juga sangat berbahaya bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi dan aktivitas ekonomi memerlukan stabilitas hukum dan kepastian regulasi, dua hal yang biasanya terganggu ketika militer mengambil alih fungsi pemerintahan. Ketidakpastian hukum, pembatasan aktivitas masyarakat, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat militer dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu roda perekonomian.
Dari sisi sosial, darurat militer berpotensi memecah belah masyarakat, terutama ketika digunakan untuk menanggapi konflik yang memiliki dimensi etnis atau agama. Militerisasi ruang publik dapat memperkuat polarisasi dan menumbuhkan rasa ketidakadilan, yang justru memperdalam konflik sosial alih-alih menyelesaikannya. Hal ini pernah terlihat dalam pengalaman di Maluku dan Poso, di mana pendekatan keamanan yang keras tanpa disertai solusi dialogis hanya memperpanjang siklus kekerasan.
Dari perspektif hukum tata negara, darurat militer juga menimbulkan bahaya terhadap prinsip rule of law. Walaupun diatur dalam undang-undang, praktik penerapan darurat militer seringkali lebih didasarkan pada pertimbangan politik ketimbang standar hukum yang objektif. Pasal-pasal dalam UU Keadaan Bahaya memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi Presiden untuk menetapkan keadaan darurat, tanpa adanya parameter yang ketat mengenai kapan suatu situasi layak disebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara yang tidak bisa ditangani dengan mekanisme biasa.
Akibatnya, terdapat risiko bahwa instrumen hukum ini digunakan secara sewenang-wenang untuk tujuan politik, misalnya menghadapi oposisi yang kuat atau menekan gerakan sosial yang menuntut perubahan. Bahaya inilah yang menempatkan darurat militer sebagai potensi ancaman terhadap prinsip konstitusionalisme di Indonesia, di mana hukum seharusnya menjadi alat pembatas kekuasaan, bukan alat untuk memperkuatnya.
Bahaya lain yang tak kalah serius adalah terhadap supremasi sipil atas militer, yang menjadi salah satu capaian penting era reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia berupaya keras menempatkan militer di bawah kendali sipil, melalui pemisahan TNI dan Polri, penghapusan dwi fungsi ABRI, serta pembatasan peran TNI dalam politik praktis. Penerapan darurat militer berpotensi membalikkan capaian ini, dengan menempatkan militer kembali sebagai aktor dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Situasi ini akan menimbulkan kemunduran dalam proses demokratisasi dan membuka jalan bagi kembalinya militerisme dalam politik Indonesia. Lebih jauh, dominasi militer dalam ruang sipil dapat menghambat pembangunan budaya politik demokratis yang inklusif, deliberatif, dan berbasis partisipasi rakyat.
Indonesia sebagai negara demokratis yang sedang tumbuh sangat bergantung pada citra positif di mata dunia, terutama dalam kaitannya dengan investasi asing, kerja sama internasional, serta posisinya dalam forum multilateral. Penerapan darurat militer dengan segala implikasinya terhadap pelanggaran HAM dan pembatasan demokrasi dapat merusak reputasi internasional Indonesia. Tekanan dari komunitas internasional dapat berbentuk sanksi ekonomi, pengurangan kerja sama, maupun kritik diplomatik yang melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global. Hal ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Negara memang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas teritorialnya. Dalam situasi ekstrem, seperti ancaman separatisme bersenjata yang meluas atau serangan militer dari luar negeri, mekanisme darurat militer mungkin dipandang sebagai langkah terakhir untuk menjaga keberlangsungan negara. Akan tetapi, dalam konteks tersebut sekalipun, bahaya dari penyalahgunaan wewenang tetap harus diwaspadai.
Mekanisme checks and balances perlu diperkuat, misalnya melalui pengawasan parlemen dan keterlibatan lembaga peradilan, agar darurat militer tidak menjadi sarana legitimasi represi yang berlebihan. Jika ditarik lebih jauh, diskursus mengenai bahaya darurat militer sesungguhnya berkaitan erat dengan pertarungan antara paradigma keamanan dan paradigma demokrasi. Paradigma keamanan menekankan stabilitas sebagai syarat utama keberlangsungan negara, sementara paradigma demokrasi menekankan partisipasi, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Ketika negara lebih condong ke paradigma keamanan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, maka darurat militer menjadi instrumen yang mudah digunakan. Sebaliknya, jika paradigma demokrasi lebih dominan, maka penetapan darurat militer akan dipandang sebagai pilihan yang sangat berbahaya dan hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi yang benar-benar ekstrem. Oleh karena itu, bahaya terbesar dari darurat militer bukan hanya pada aspek praktis penerapannya, tetapi juga pada bagaimana ia mencerminkan orientasi politik suatu rezim.
Dalam konteks sejarah Indonesia, pengalaman masa lalu memberikan pelajaran bahwa penggunaan instrumen darurat militer seringkali lebih menimbulkan kerugian jangka panjang dibandingkan manfaat sesaat. Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan rule of law harus selalu dijadikan pedoman utama dalam menghadapi situasi krisis.
Negara perlu mengembangkan mekanisme alternatif untuk merespons ancaman keamanan, misalnya dengan memperkuat kapasitas lembaga sipil, meningkatkan kualitas dialog politik, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai. Hanya dengan demikian Indonesia dapat menghindari bahaya laten dari penetapan darurat militer, sekaligus menjaga konsistensi perjalanan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
Penulis: Suud Sarim Karimullah