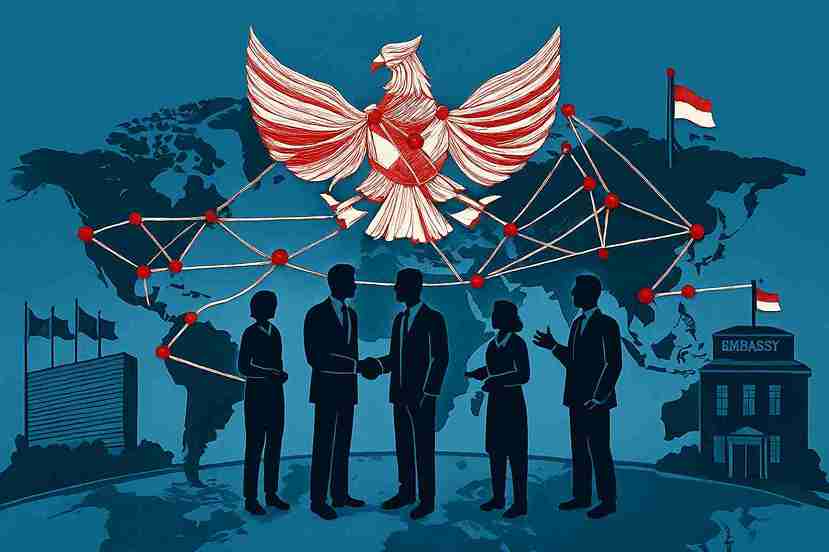Kriminalisasi kemiskinan dalam hukum pidana di Indonesia merupakan realitas yang paradoksal dan ironis, karena hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kelompok rentan justru sering kali berubah menjadi mekanisme represif yang menindas mereka yang berada di lapisan terbawah masyarakat. Fenomena ini tidak hadir secara eksplisit dalam teks hukum yang menyatakan bahwa miskin adalah kejahatan, tetapi termanifestasi melalui cara hukum pidana ditegakkan, ditafsirkan, dan dipraktikkan.
Kemiskinan, yang sesungguhnya merupakan problem struktural hasil dari ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi, diperlakukan seakan-akan sebagai kegagalan individual yang pantas dihukum. Dengan demikian, hukum pidana bukan lagi sekadar arena penegakan norma, melainkan ruang reproduksi ketidakadilan sosial yang melegitimasi stigmatisasi kemiskinan. Konteks inilah yang membuat pembahasan kriminalisasi kemiskinan menjadi sangat penting, karena ia menyentuh inti persoalan keadilan substantif dalam sebuah negara hukum.
Kriminalisasi kemiskinan dapat terlihat dari pola selektivitas dalam penegakan hukum pidana. Rakyat miskin jauh lebih mungkin terjerat hukum pidana dibandingkan kelompok kaya. Seseorang yang melakukan pencurian kecil karena lapar, misalnya mengambil makanan di minimarket atau mencuri sandal di rumah ibadah, seringkali dihukum penjara dengan alasan menjaga ketertiban hukum.
Sementara itu, kejahatan kerah putih seperti korupsi, penggelapan pajak, atau manipulasi kebijakan yang nilainya miliaran hingga triliunan rupiah justru sering diselesaikan dengan hukuman ringan, fasilitas mewah dalam penjara, atau bahkan berujung pada impunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak netral, melainkan bekerja secara diskriminatif dengan menempatkan orang miskin sebagai target utama penegakan hukum, sementara orang kaya relatif kebal terhadap jeratan pidana.
Selain itu, kriminalisasi kemiskinan juga tampak dari aturan-aturan pidana yang secara substansial menjerat aktivitas yang identik dengan orang miskin. Misalnya, peraturan daerah tentang ketertiban umum di berbagai kota melarang gelandangan, pengemis, atau pedagang kaki lima untuk berada di ruang publik tertentu. Dengan dalih menjaga ketertiban dan keindahan kota, kelompok miskin yang mencari nafkah di ruang publik diperlakukan sebagai pelanggar hukum. Padahal, kehadiran mereka adalah manifestasi dari kegagalan negara menyediakan lapangan kerja layak, perumahan yang terjangkau, atau jaminan sosial yang memadai.
Alih-alih mengatasi akar struktural kemiskinan, negara justru menggunakan hukum pidana untuk mengusir mereka dari ruang publik, seakan-akan keberadaan orang miskin adalah masalah kriminal yang harus diberantas. Inilah wajah nyata kriminalisasi kemiskinan, di mana hukum pidana berfungsi bukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, melainkan untuk melindungi kenyamanan kelas menengah dan elite dari “gangguan” visual maupun sosial yang ditimbulkan oleh kemiskinan.
Kriminalisasi kemiskinan juga hadir dalam praktik penahanan pra-persidangan yang sering menjerat orang miskin. Mereka yang tidak mampu membayar uang jaminan atau biaya advokasi lebih sering ditahan, meskipun perkara yang dihadapi tergolong ringan. Sementara itu, bagi orang kaya, akses terhadap penasihat hukum berkualitas, uang jaminan, dan jaringan kekuasaan memungkinkan mereka menghindari penahanan atau bahkan memanipulasi proses hukum.
Kebebasan seseorang dalam sistem pidana tidak ditentukan semata oleh berat ringannya tindak pidana, melainkan oleh kapasitas ekonominya. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa hukum pidana secara struktural menciptakan kriminalisasi kemiskinan, karena orang miskin diperlakukan sebagai pihak yang harus dibatasi kebebasannya sejak awal, sementara orang kaya mendapatkan toleransi. Hal ini memperlihatkan bahwa pidana, yang semestinya didasarkan pada prinsip keadilan, berubah menjadi mekanisme eksklusif yang melanggengkan stratifikasi sosial.
Dalam banyak putusan pengadilan atau retorika aparat penegak hukum, orang miskin sering dipersepsikan sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Narasi ini membangun persepsi publik bahwa kemiskinan identik dengan kriminalitas, sehingga menguatkan justifikasi terhadap kebijakan represif.
Padahal, berbagai studi kriminologi menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah penyebab tunggal kejahatan, melainkan akibat dari struktur ketidakadilan yang lebih luas, seperti ketimpangan distribusi sumber daya, eksklusi sosial, dan diskriminasi. Kriminalisasi kemiskinan bukan sekadar kesalahan teknis dalam hukum pidana, melainkan hasil dari ideologi yang melihat kemiskinan sebagai deviasi dari norma sosial dominan. Ideologi inilah yang kemudian memengaruhi legislasi, kebijakan publik, hingga putusan pengadilan, sehingga kemiskinan terus diperlakukan sebagai masalah kriminal, bukan masalah sosial.
Fenomena ini juga dapat dipahami melalui perspektif teori hukum kritis yang melihat hukum sebagai instrumen kekuasaan. Dalam kerangka ini, hukum pidana bukan sekadar perangkat normatif untuk menjaga ketertiban, melainkan mekanisme untuk melanggengkan dominasi kelas tertentu.
Di Indonesia, hukum pidana sering kali digunakan untuk menjaga stabilitas sosial-politik yang menguntungkan kelompok elite, dengan mengorbankan kelompok miskin. Contoh nyata adalah penggunaan hukum pidana terhadap masyarakat adat atau petani miskin yang mempertahankan tanahnya dari ekspansi perkebunan atau tambang. Mereka kerap dituduh melakukan perusakan, penyerobotan lahan, atau penghasutan, padahal sesungguhnya mereka hanya berusaha mempertahankan hak hidup. Sementara itu, perusahaan besar yang merusak lingkungan dan menggusur masyarakat lokal jarang disentuh hukum pidana.
Dalam rezim neoliberalisme, negara semakin mendorong deregulasi ekonomi dan privatisasi, yang berujung pada semakin minimnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, negara memperkuat perangkat hukum pidana untuk mengendalikan populasi miskin yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas pasar.
Aparatus hukum pidana dipakai untuk menertibkan ruang kota, membersihkan kawasan dari “pengganggu” seperti pengemis atau pedagang informal, dan memastikan iklim investasi tetap kondusif. Dengan demikian, kriminalisasi kemiskinan bukanlah kebijakan yang netral, melainkan bagian dari strategi neoliberal yang memarginalisasi kelompok miskin secara sistematis melalui hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi global yang terus mendorong negara untuk lebih represif terhadap kelompok miskin.
Selain dimensi struktural dan ideologis, kriminalisasi kemiskinan juga melahirkan dampak sosial yang sangat serius. Pertama, ia memperkuat siklus kemiskinan, karena orang miskin yang terjerat hukum pidana kehilangan kesempatan untuk memperbaiki nasibnya. Hukuman penjara, meskipun untuk tindak pidana ringan, menimbulkan stigma sosial yang membuat mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali dalam komunitas.
Kedua, kriminalisasi kemiskinan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat miskin terhadap negara. Mereka melihat hukum bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Hal ini dapat memicu alienasi politik dan bahkan perlawanan yang lebih radikal terhadap negara.
Ketiga, kriminalisasi kemiskinan juga menurunkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan, karena masyarakat luas menyadari ketidakadilan yang terjadi, bahwa hukum lebih berpihak pada yang kuat daripada pada yang lemah. Dampak ini semua menunjukkan bahwa kriminalisasi kemiskinan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak fondasi keadilan sosial dan kohesi masyarakat.
Dalam perspektif filosofis, kriminalisasi kemiskinan menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuan hukum pidana itu sendiri. Jika tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang esensial, seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan, maka mengapa aktivitas bertahan hidup orang miskin justru dipidana? Apakah hukum pidana telah menyimpang dari misinya dan berubah menjadi instrumen penindasan?
Pertanyaan ini mengarah pada kritik mendalam bahwa hukum pidana di Indonesia sering kali lebih berfungsi menjaga ketertiban semu daripada menghadirkan keadilan substantif. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban bagi kelas menengah dan elite, yang merasa terganggu oleh keberadaan miskin di ruang publik. Dengan demikian, kriminalisasi kemiskinan memperlihatkan bahwa hukum pidana telah kehilangan orientasi moralnya, karena ia lebih peduli pada stabilitas sosial yang artifisial daripada keadilan bagi manusia.
Meskipun fenomena kriminalisasi kemiskinan sangat kuat, bukan berarti tidak ada ruang untuk resistensi dan perubahan. Gerakan masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan akademisi hukum telah berulang kali mengkritik praktik ini, mendorong perubahan regulasi, dan melakukan advokasi bagi korban kriminalisasi. Judicial review terhadap peraturan daerah yang diskriminatif, kampanye untuk dekriminalisasi aktivitas informal, serta advokasi hak-hak masyarakat miskin di pengadilan merupakan bentuk perlawanan yang membuka ruang perubahan.
Selain itu, pemikiran progresif dalam ilmu hukum pidana juga mulai menekankan pentingnya dekriminalisasi dan restorasi sosial dibandingkan represifitas. Pendekatan restorative justice, misalnya, berusaha menghadirkan solusi yang lebih adil dengan memperbaiki relasi sosial daripada menghukum. Dengan demikian, meskipun kriminalisasi kemiskinan adalah kenyataan pahit, masih ada peluang untuk mengubah arah hukum pidana agar lebih humanis dan adil.
Penulis: Suud Sarim Karimullah