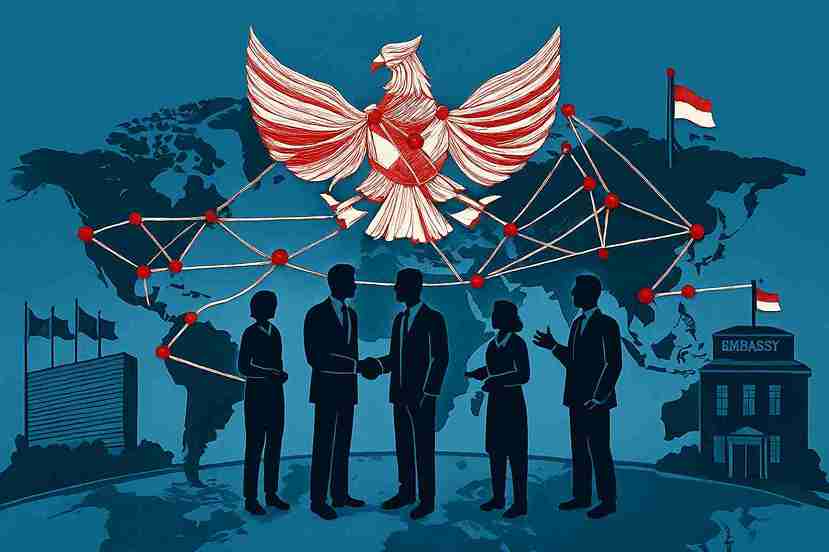Ustaz medsos merupakan fenomena kontemporer yang menyingkap bagaimana transformasi teknologi digital menggeser lanskap otoritas keagamaan dan membentuk ulang cara publik Muslim mengakses, menilai, dan menginternalisasi pesan-pesan religius. Jika sebelumnya legitimasi ustaz bertumpu pada sanad keilmuan, kedalaman literatur klasik, serta pengakuan institusi pendidikan Islam formal, kini popularitas di media sosial sering kali menjadi pintu utama pengaruh.
Viralitas menjadikan seorang ustaz bukan sekadar penceramah, melainkan figur publik yang merangkap peran sebagai kreator konten, influencer, bahkan selebritas yang bersaing di ruang algoritmik. Dalam medan ini, agama tidak lagi hanya tampil sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai komoditas visual dan narasi singkat yang disesuaikan dengan logika konsumsi digital.
Fenomena ustaz medsos viral dapat dibaca sebagai pergeseran otoritas dari kurasi institusional ke algoritma platform. Konten dakwah yang dulunya melalui proses seleksi redaksional majalah, penerbit, atau panitia taklim, kini diseleksi oleh mesin rekomendasi yang hanya mengenal angka melalui jumlah like, komentar, dan waktu tonton. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang mengundang keterlibatan emosional tinggi, baik berupa kekaguman, keterkejutan, maupun kemarahan dan mengabaikan konten yang lebih kompleks tetapi kurang memancing reaksi instan.
Di sini, ustaz medsos viral menghadapi dilema epistemologis sebab bagaimana menjaga kedalaman makna di tengah tekanan untuk selalu cepat, ringkas, dan dramatis. Apabila ia terlalu hati-hati, publik bisa beralih ke ustaz lain yang lebih menghibur namun jika ia tergoda untuk memangkas nuansa demi viralitas, ia berisiko mereduksi kompleksitas agama menjadi slogan atau meme.
Keberhasilan seorang ustaz menjadi viral di medsos juga terkait erat dengan kecakapannya membangun relasi parasosial. Pengikut tidak hanya mendengarkan tausiyahnya, tetapi juga merasa dekat karena disuguhi potongan kehidupan pribadi, aktivitas keluarga, perjalanan dakwah, gaya hidup, bahkan momen rehat. Keintiman yang terkurasi ini menumbuhkan loyalitas yang lebih dalam daripada sekadar persetujuan terhadap isi ceramah.
Bagi sebagian pengikut, membela sang ustaz sama artinya dengan membela identitas diri. Hal ini menghadirkan potensi positif, seperti mobilisasi cepat untuk kegiatan filantropi dan solidaritas sosial, tetapi juga risiko negatif berupa fanatisme personal, sebab kritik terhadap argumen dianggap sebagai serangan terhadap sosok. Publik Muslim akhirnya berhadapan dengan tantangan baru yang membedakan antara otoritas keilmuan yang sah dengan daya tarik personalitas yang memikat.
Dimensi ekonomi pun tidak bisa dipisahkan. Kanal dakwah digital yang besar memerlukan sumber daya signifikan dengan kamera berkualitas tinggi, tim editing, desain grafis, manajemen media, bahkan strategi pemasaran. Untuk menopang semua itu, sebagian ustaz medsos viral menggandeng sponsor dan iklan. Inilah titik rawan di mana batas antara dakwah dan komodifikasi kabur.
Ketika pesan agama diselipkan bersama promosi produk, publik kesulitan menilai apakah sebuah anjuran bersifat murni religius atau dipengaruhi kontrak komersial. Ketidaktransparanan semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan. Karena itu, transparansi finansial dan penandaan konten berbayar seharusnya menjadi etika dasar. Dalam hal ini, ustaz medsos yang berkomitmen pada integritas akan berupaya menjaga jarak antara pesan keagamaan dan kepentingan komersial, atau setidaknya menyatakannya secara terbuka.
Dalam konteks generasi muda, ustaz medsos menempati ruang yang strategis sekaligus rapuh. Anak muda Muslim yang tumbuh dengan budaya TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts terbiasa mengonsumsi pengetahuan dalam format potongan singkat. Mereka lebih mudah menginternalisasi pesan moral yang dikemas dengan estetika visual, humor, atau musik latar daripada kuliah panjang yang sarat teks klasik.
Ustaz medsos yang peka terhadap tren ini mampu meraih simpati generasi muda dengan gaya bahasa yang santai dan visual yang menarik. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan pesan yang sampai tetap bernuansa, tidak terjebak pada simplifikasi ekstrem yang mengorbankan akurasi. Dalam hal ini, kepekaan desain perlu bersanding dengan komitmen epistemologis agar agama tidak direduksi menjadi sekadar hiburan digital.
Fenomena ini juga bersinggungan dengan dinamika politik identitas. Di banyak kasus, popularitas ustaz medsos meningkat bukan hanya karena kualitas materi dakwah, melainkan karena ia berhasil menyuarakan aspirasi kelompok tertentu. Isu-isu seperti gaya busana, musik, politik internasional, atau perbedaan mazhab sering dimanfaatkan untuk membangun citra sebagai pembela kebenaran dan identitas Muslim.
Viralitas pun diproduksi melalui polarisasi dengan menguatkan rasa “kita” melawan “mereka”. Dampaknya, opini publik Muslim dapat dengan cepat terfragmentasi, di mana setiap kelompok merasa memiliki ustaznya sendiri yang memperkuat pandangan dunia mereka. Alih-alih menjadi jembatan, ustaz medsos terkadang berfungsi sebagai generator ruang gema, memperkuat bias konfirmasi dan mengikis semangat musyawarah.
Pergeseran otoritas keagamaan ke ruang medsos juga menghadirkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas. Jika seorang ustaz di mimbar salah ucap, koreksi biasanya datang dari sesama ulama atau pengurus masjid, dan dampaknya terbatas pada jamaah yang hadir. Namun, kesalahan ustaz medsos segera menyebar ke jutaan penonton, dipotong, dipelintir, dan disebarkan ulang.
Klarifikasi sering kali datang terlambat dan kalah cepat dari rumor. Untuk itu, diperlukan mekanisme akuntabilitas baru: standar etik produksi konten, komitmen koreksi publik yang terlihat, serta sistem verifikasi rujukan yang memudahkan audiens menelusuri sumber. Akuntabilitas bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk memastikan bahwa pengaruh besar yang dimiliki ustaz medsos diimbangi oleh tanggung jawab epistemik yang setara.
Di sisi lain, potensi kebaikan dari keberadaan ustaz medsos tidak bisa diremehkan. Media sosial memungkinkan penggalangan solidaritas dengan skala dan kecepatan yang luar biasa. Dalam bencana alam, misalnya, ustaz dapat menggerakkan jutaan pengikut untuk berdonasi dalam hitungan jam. Dalam isu kemanusiaan internasional, ia dapat membangkitkan simpati lintas batas negara dan bahasa.
Ia juga dapat membuka ruang dialog lintas generasi antara anak muda yang mungkin enggan datang ke pengajian tatap muka tetap bisa belajar melalui ponsel mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, ustaz medsos bisa menjadi agen perubahan sosial yang memperluas kesadaran kolektif tentang zakat, wakaf, keadilan, atau pentingnya menjaga lingkungan. Viralitas yang digunakan dengan bijak dapat menjadi akselerator kesalehan sosial. Namun, semua potensi itu hanya bisa diwujudkan bila ustaz medsos berani mengafirmasi batas pengetahuannya.
Mengakui bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab instan, bahwa sebagian isu membutuhkan penelitian lebih lanjut, dan bahwa terdapat wilayah perbedaan pandangan yang sah adalah bagian dari tanggung jawab. Transparansi rujukan harus menjadi standar dengan menyebut kitab, hadis, atau ulama rujukan lengkap dengan konteks penafsirannya. Tindakan semacam ini bukan hanya mendidik audiens, tetapi juga meneguhkan kredibilitas ustaz sebagai bagian dari jaringan keilmuan Islam, bukan sekadar penghibur digital.
Fenomena ustaz medsos memaksa kita meninjau ulang definisi otoritas, etika, dan tanggung jawab dalam era platform. Ia membuka peluang besar untuk menjangkau generasi baru, memperluas solidaritas, dan menyebarkan pengetahuan. Namun ia juga menghadirkan risiko simplifikasi, komodifikasi, dan polarisasi.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah fenomena ini baik atau buruk, melainkan bagaimana kita bersama-sama membentuk ekosistem yang menyehatkan. Jika kita membiarkan algoritma bekerja sendiri, ia akan terus mengangkat yang paling memecah. Tetapi jika kita merancang etos baru yang mengutamakan adab, transparansi, dan tanggung jawab, maka ustaz medsos dapat menjadi simbol era baru dan bukan sekadar selebritas digital, melainkan penghubung antara tradisi ilmu dengan ritme zaman, yang memuliakan akal, menentramkan hati, dan menumbuhkan kesalehan sosial.
Penulis: Suud Sarim Karimullah