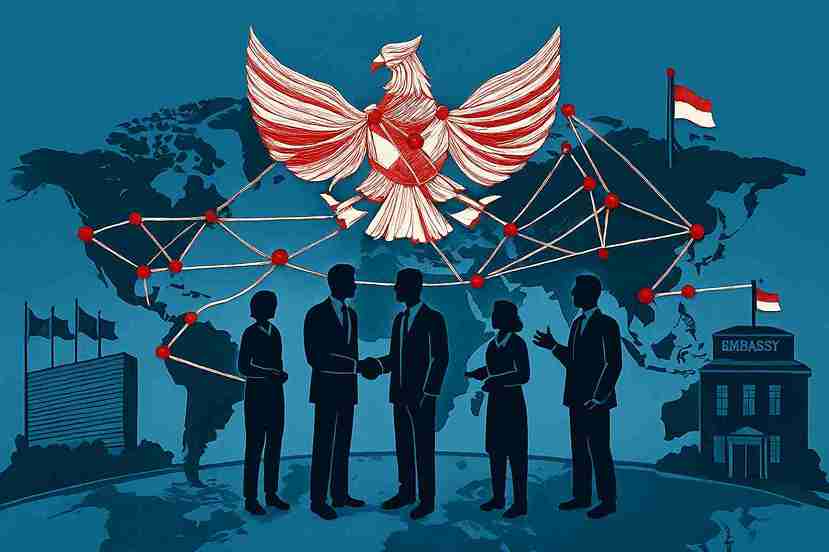Diskriminasi struktural dalam hukum nasional di Indonesia merupakan fenomena yang tidak sekadar terletak pada praktik individual yang bersifat diskriminatif, melainkan tertanam dalam konstruksi kelembagaan, kerangka normatif, serta mekanisme birokrasi negara yang pada dasarnya menciptakan hierarki akses terhadap keadilan, hak, dan peluang. Diskriminasi struktural ini bekerja secara sistematis dan seringkali tersamar di balik klaim netralitas hukum, sehingga sulit diidentifikasi hanya dengan melihat teks normatif semata.
Ia melekat dalam proses legislasi, interpretasi, maupun implementasi hukum, serta diperkuat oleh relasi kuasa politik, ekonomi, dan sosial yang terbangun dalam sejarah panjang Indonesia sebagai negara-bangsa. Karena itu, membicarakan diskriminasi struktural dalam hukum nasional berarti membicarakan bagaimana hukum, alih-alih menjadi instrumen keadilan sosial, justru kerap menjadi instrumen reproduksi ketidakadilan.
Salah satu wajah paling jelas dari diskriminasi struktural dapat ditemukan dalam kebijakan hukum yang membedakan perlakuan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis, agama, atau gender. Misalnya, pengaturan administratif terkait KTP di masa lalu yang mencantumkan kolom agama secara rigid telah menempatkan kelompok agama minoritas dalam posisi rentan.
Mereka yang tidak menganut salah satu dari enam agama resmi seringkali mengalami kesulitan administratif, mulai dari pencatatan pernikahan, akses pendidikan, hingga hak sipil lainnya. Walaupun Mahkamah Konstitusi kemudian memberi putusan yang lebih inklusif terkait pengakuan kepercayaan, fakta bahwa diskriminasi tersebut bertahan begitu lama menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk melegitimasi eksklusi sosial. Di sini hukum tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga aktif membentuk struktur ketidakadilan.
Fenomena diskriminasi gender juga sangat jelas terlihat dalam produk hukum nasional. Banyak regulasi yang pada permukaannya tampak netral, tetapi sesungguhnya mengandung bias gender yang mendalam. Hukum perkawinan, misalnya, dalam beberapa pasalnya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam hal relasi rumah tangga maupun dalam akses terhadap perceraian dan hak asuh anak.
Mahkamah Konstitusi memang telah memutuskan beberapa uji materi terkait batas usia perkawinan, tetapi problem struktural dalam regulasi tersebut tetap menegaskan konstruksi patriarkis yang mengakar. Diskriminasi ini bukan hanya pada level teks hukum, melainkan pada implementasinya di pengadilan dan praktik administrasi yang kerap lebih berpihak pada posisi laki-laki.
Diskriminasi struktural juga muncul dalam ranah ekonomi melalui hukum dan regulasi yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Kebijakan hukum agraria seringkali lebih menguntungkan korporasi besar dibanding masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah menempati wilayah tertentu selama ratusan tahun kerap digusur dengan dalih legalitas konsesi perusahaan, karena hukum positif tidak mengakui klaim adat kecuali dalam batasan yang sangat sempit.
Kasus-kasus konflik agraria yang berulang di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti nyata bagaimana struktur hukum lebih berpihak pada kapital dan negara ketimbang pada komunitas yang lemah secara politik. Di sini, hukum bukan sekadar netral dalam menyelesaikan konflik, tetapi hadir sebagai instrumen yang melanggengkan ketidaksetaraan struktural dengan memihak pada aktor ekonomi besar.
Dimensi diskriminasi yang lain juga tampak dalam sistem peradilan pidana. Data menunjukkan bahwa kelompok miskin dan marjinal lebih sering terjebak dalam sistem hukum pidana dibanding kelompok kaya dan berpengaruh. Hal ini tidak hanya terkait dengan kemampuan finansial dalam mengakses penasihat hukum yang berkualitas, tetapi juga terkait dengan kultur aparat penegak hukum yang kerap menggunakan hukum sebagai sarana represif.
Seseorang dari kalangan miskin yang melakukan tindak pidana ringan bisa mendapatkan hukuman penjara, sementara pelaku korupsi kelas kakap dapat menikmati berbagai privilese hukum hingga remisi. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan bahwa hukum di Indonesia seringkali bekerja secara selektif, menegakkan hukum dengan keras kepada yang lemah, dan lunak terhadap yang berkuasa. Fenomena ini bukan sekadar praktik penyalahgunaan, melainkan cerminan dari diskriminasi struktural yang melekat dalam relasi kuasa antara hukum, politik, dan ekonomi.
Diskriminasi struktural juga dilembagakan melalui regulasi birokrasi yang tampak administratif, tetapi berimplikasi luas terhadap hak warga negara. Misalnya, aturan-aturan kependudukan yang menuntut dokumen tertentu sebagai syarat administrasi seringkali menyulitkan kelompok rentan, seperti masyarakat adat, masyarakat di daerah terpencil, atau kelompok miskin kota yang tidak memiliki akses formal ke dokumen tersebut.
Akibatnya, mereka kehilangan akses pada berbagai layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak harus hadir dalam bentuk larangan eksplisit, melainkan bisa bekerja secara halus melalui syarat administratif yang hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang sudah memiliki akses terhadap sumber daya.
Diskriminasi dalam hukum nasional Indonesia juga berakar pada cara pandang negara terhadap pluralisme. Slogan Bhinneka Tunggal Ika seringkali hanya menjadi retorika, sementara hukum justru mempersempit ruang bagi ekspresi keberagaman. Misalnya, regulasi terkait kebebasan beragama kerap lebih menekankan pada stabilitas dan ketertiban umum ketimbang perlindungan hak minoritas.
Hal ini menciptakan situasi di mana kelompok minoritas berulang kali menjadi korban intoleransi tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar gagal netral, melainkan secara aktif mengafirmasi mayoritarianisme, yang merupakan bentuk diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas.
Kondisi diskriminasi struktural ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan warisan kolonial. Banyak kerangka hukum nasional yang masih mewarisi struktur diskriminatif dari era Hindia Belanda, di mana hukum digunakan untuk membedakan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.
Walaupun kategori tersebut sudah tidak ada secara formal, logika pemisahan, hierarki, dan diferensiasi tetap bertahan dalam bentuk lain. Misalnya, perbedaan perlakuan terhadap pekerja formal dan informal, atau masyarakat kota dan desa, masih mereproduksi ketidaksetaraan yang berakar dari konstruksi hukum kolonial.
Di era kontemporer, diskriminasi struktural dalam hukum nasional juga semakin terkait dengan globalisasi dan dinamika neoliberalisme. Regulasi yang mendukung investasi asing dan liberalisasi ekonomi seringkali mengabaikan hak-hak dasar pekerja atau masyarakat lokal. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru lebih berfungsi sebagai instrumen untuk memfasilitasi arus modal global.
Contohnya, berbagai undang-undang terkait investasi dan omnibus law cenderung lebih berorientasi pada kemudahan usaha ketimbang perlindungan hak buruh dan lingkungan. Di sini terlihat bagaimana hukum nasional menjadi bagian dari struktur global yang mendiskriminasi kelompok rentan, terutama kelas pekerja dan masyarakat adat yang posisinya semakin terpinggirkan.
Membicarakan diskriminasi struktural dalam hukum nasional Indonesia berarti juga mempertanyakan klaim universalitas dan netralitas hukum itu sendiri. Dalam teori hukum modern, hukum sering dipahami sebagai sistem normatif yang rasional dan netral. Namun dalam praktik, hukum di Indonesia sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi yang melekat dalam proses pembentukannya.
Legislasi yang lahir di parlemen kerap merupakan hasil kompromi politik yang mengutamakan kepentingan elite, sehingga hukum yang dihasilkan sudah mengandung bias struktural sejak awal. Proses ini diperparah dengan lemahnya mekanisme partisipasi publik yang seharusnya menjadi sarana korektif terhadap potensi diskriminasi.
Perlawanan terhadap diskriminasi struktural dalam hukum terus berkembang. Gerakan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan kelompok akademisi secara konsisten melakukan kritik dan mendorong reformasi hukum. Misalnya, desakan untuk merevisi undang-undang yang diskriminatif, seperti UU Perkawinan, UU Minerba, atau UU Cipta Kerja, merupakan bentuk upaya untuk membongkar diskriminasi yang tertanam dalam hukum nasional.
Mahkamah Konstitusi juga kerap menjadi arena penting dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak kelompok minoritas, meskipun tidak semua putusan berpihak pada kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diskriminasi struktural sangat kuat, ada juga dinamika perlawanan yang membuka ruang untuk transformasi hukum ke arah yang lebih inklusif.
Diskriminasi struktural dalam hukum nasional di Indonesia sesungguhnya bukan sekadar problem teknis dalam sistem hukum, melainkan problem ideologis yang terkait dengan cara negara mendefinisikan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi. Selama hukum dipahami sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepentingan mayoritas, diskriminasi akan terus dilembagakan.
Sebaliknya, hukum hanya dapat menjadi instrumen keadilan apabila ia diposisikan untuk melindungi yang lemah dan minoritas dari dominasi mayoritas. Tantangannya adalah bagaimana merekonstruksi hukum nasional agar mampu membongkar ketidakadilan struktural dan menghadirkan keadilan substantif bagi semua warga negara, bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi.