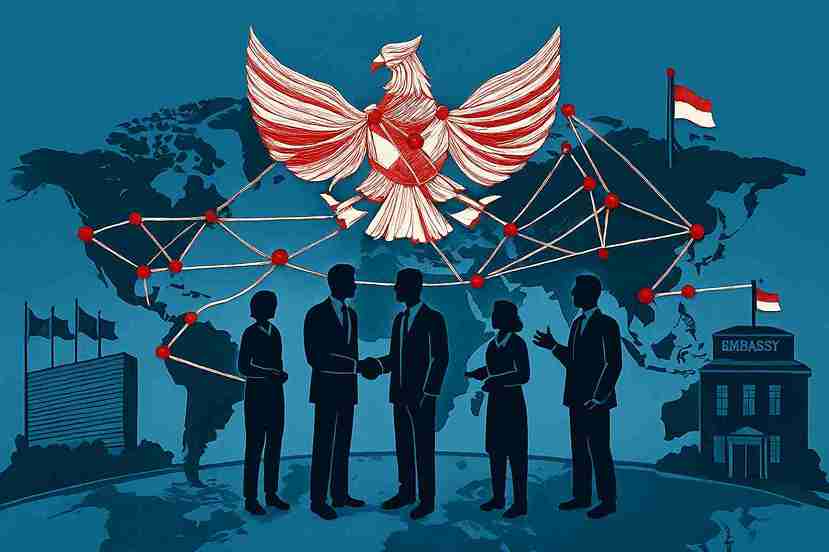Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menjadi sosok yang dalam lintasan sejarah Islam tak hanya dipandang sebagai seorang syahid di padang Karbala, tetapi juga sebagai simbol abadi perlawanan terhadap tirani, ketidakadilan, dan manipulasi politik yang berbalut agama. Kisahnya telah melampaui sekadar peristiwa politik abad ketujuh; ia menjelma menjadi teriakan kebenaran yang terus bergema lintas generasi, lintas batas geografis, bahkan lintas sekat ideologis.
Tragedi Karbala yang terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriyah bukanlah sekadar peperangan kecil antara pasukan kecil Husein dan tentara besar Yazid bin Muawiyah. Ia merupakan titik kritis yang memperlihatkan betapa kuasa dapat menindas moralitas, betapa politik dapat mengorbankan agama, dan betapa keberanian moral seorang individu dapat mengalahkan dominasi ribuan tentara bersenjata lengkap. Padang Karbala menjadi saksi bisu bagaimana darah seorang cucu Nabi ditumpahkan, tetapi darah itu justru berubah menjadi tinta sejarah yang mengabadikan makna perlawanan.
Husein tidak menjeritkan kebenaran melalui retorika kosong, melainkan dengan pengorbanan dirinya, keluarganya, dan pengikutnya. Keputusannya untuk menolak baiat kepada Yazid bukanlah sikap keras kepala yang irasional, melainkan bentuk konsistensi pada prinsip keadilan dan moralitas Islam. Bagi Husein, kekuasaan tidak boleh diwariskan dengan cara pewarisan monarki yang bertentangan dengan nilai syura dan musyawarah dalam Islam.
Ketika Yazid menuntut legitimasi dari Husein, ia sadar bahwa persetujuan itu akan menjadi pembenaran atas penyalahgunaan agama untuk melanggengkan dinasti politik. Dengan menolak, Husein tahu dirinya menantang kekuatan besar, tetapi pada saat yang sama ia menegakkan garis pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Inilah yang menjadikan teriakannya bukan sekadar suara protes, melainkan suara nurani umat yang disuarakan di tengah ancaman maut.
Perjalanan Husein menuju Karbala menggambarkan betapa ia sadar bahwa langkahnya adalah menuju pengorbanan. Surat-surat dari Kufah yang mengundangnya datang dengan janji dukungan ternyata berbalik menjadi jebakan, karena kekuatan politik Yazid menekan masyarakat Kufah hingga mereka mengkhianati janji mereka. Husein tetap melanjutkan perjalanan, bukan karena keliru membaca peta politik, melainkan karena ia meyakini bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, melainkan oleh integritas moral.
Dalam pandangan ini, keberanian Husein melampaui kalkulasi politik praktis; ia berdiri di atas moralitas profetik. Ia tahu bahwa pertempuran itu tidak akan dimenangkan di arena fisik, tetapi akan dimenangkan di arena sejarah dan nurani manusia. Karbala, dengan demikian, menjadi panggung simbolik tempat pertarungan kebenaran dan kebatilan diperlihatkan dalam bentuk paling telanjang.
Ketika pasukan Yazid mengepung dan memutus akses air bagi keluarga Husein, tragedi itu mencapai puncaknya sebagai gambaran kezaliman. Anak-anak kecil yang kehausan, wanita-wanita yang ketakutan, dan para sahabat yang tetap teguh mendampingi menunjukkan dimensi kemanusiaan tragedi tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Husein merespons situasi ini. Ia tidak menyerah, tidak mundur, dan tidak berkompromi.
Ia menegaskan bahwa hidup dengan kehinaan lebih buruk daripada mati dengan kemuliaan. Kalimatnya yang terkenal, “Aku tidak bangkit karena ambisi kekuasaan, melainkan untuk menegakkan agama kakekku dan meluruskan penyimpangan,” adalah pernyataan yang menegaskan betapa perjuangannya bukan sekadar konflik politik, tetapi misi moral. Ia menjadikan kematian sebagai instrumen untuk menghidupkan kembali nurani umat yang tengah dibungkam oleh kekuasaan zalim.
Pertempuran pada hari Asyura menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Pasukan Husein hanya berjumlah puluhan orang, sementara pasukan Yazid mencapai ribuan. Namun, dalam ketimpangan itu lahirlah narasi heroik. Satu demi satu sahabat Husein gugur dengan gagah berani, sementara Husein sendiri terus bertahan hingga titik darah penghabisan.
Kematian mereka bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan simbolik. Karena sejak saat itu, Yazid mungkin berkuasa secara politik, tetapi Husein menguasai sejarah moral umat Islam. Nama Yazid dikenang dengan stigma kebatilan, sementara Husein dikenang dengan kemuliaan yang abadi. Inilah paradoks Karbala dengan pihak yang secara militer menang, tetapi secara moral kalah dan pihak yang secara fisik kalah, tetapi secara spiritual menang.
Teriakan kebenaran Husein di Karbala tidak berhenti pada peristiwa abad ketujuh itu. Ia terus bergema sepanjang sejarah. Dari perspektif sosiologis, tragedi Karbala menjadi sumber inspirasi bagi berbagai gerakan perlawanan terhadap tirani. Di berbagai belahan dunia Islam, kisah Husein digunakan untuk membakar semangat rakyat melawan kolonialisme, diktator, dan penindasan sosial.
Karbala menjadi paradigma bahwa kekuatan moral bisa menjadi energi transformasi sosial. Bahkan di luar dunia Islam, tragedi ini menjadi simbol universal perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak tokoh dunia yang mengagumi keberanian Husein. Mahatma Gandhi misalnya, pernah menyatakan bahwa ia belajar dari Husein bagaimana menjadi seorang minoritas yang berani melawan mayoritas penindas demi kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Karbala tidak terikat oleh batas mazhab atau agama sebab ia adalah warisan kemanusiaan. Namun, makna Karbala tidak berhenti pada romantisme perlawanan. Ia juga menuntut refleksi kritis terhadap realitas sosial-politik.
Pertanyaan yang muncul adalah: apakah umat Islam hari ini masih setia pada spirit Husein atau justru tergoda untuk meniru model Yazid dalam berpolitik? Apakah institusi keagamaan benar-benar menjadi suara moral atau malah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan? Karbala mengingatkan bahwa keberpihakan pada kebenaran seringkali menuntut pengorbanan yang besar, dan bahwa kompromi dengan kebatilan akan menghasilkan kehinaan jangka panjang. Di sinilah kompleksitas Karbala sebagai pelajaran hidup, ia bukan sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi cermin yang menyingkap wajah masa kini.
Dalam konteks filsafat sejarah, tragedi Karbala dapat dipahami sebagai momen dialektis antara tesis kekuasaan absolut Yazid dan antitesis moralitas Husein. Sintesis dari keduanya adalah lahirnya kesadaran kolektif umat bahwa agama tidak boleh ditundukkan pada politik praktis. Kesadaran ini menjalar dalam berbagai bentuk ritual, literatur, dan budaya, terutama dalam tradisi peringatan Asyura. Peringatan itu bukan sekadar ritual kesedihan, tetapi juga momentum untuk memperbarui komitmen pada nilai-nilai keadilan.
Karbala juga memunculkan paradoks eksistensial: bagaimana mungkin kematian yang begitu tragis justru melahirkan kehidupan yang begitu bermakna? Di sini, Husein menghadirkan logika lain: kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru dalam ingatan sejarah. Ia memilih mati agar kebenaran hidup, dan karena itu ia tetap hidup dalam setiap perlawanan terhadap ketidakadilan.
Teriakan kebenaran yang ia suarakan bukanlah teriakan putus asa, melainkan deklarasi optimisme bahwa sekalipun tubuh bisa hancur, nilai-nilai luhur tidak bisa dibunuh. Spirit ini yang menjadikan Karbala relevan bagi siapapun yang menolak tunduk pada tirani, baik tirani politik, tirani ekonomi, maupun tirani ideologis.
Dalam kerangka etika, Husein mengajarkan bahwa keberanian moral lebih penting daripada kompromi pragmatis. Ia bisa saja menerima baiat kepada Yazid dan hidup tenang dalam kemewahan, tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Pilihan itu membuatnya kehilangan hidup duniawi, tetapi memberinya kehidupan abadi dalam sejarah.
Teriakan kebenaran di Karbala juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Ia bukan sekadar perlawanan politik, melainkan jihad eksistensial melawan segala bentuk penyimpangan. Husein menegaskan bahwa ibadah tidak hanya berupa ritual, tetapi juga keberanian untuk berkata tidak pada kezaliman. Inilah yang membuat tragedi Karbala begitu memikat sebab ia memperlihatkan bagaimana iman dapat diwujudkan dalam bentuk paling konkret, yakni pengorbanan total.
Jika direnungkan secara lebih luas, tragedi Karbala adalah pengingat bahwa sejarah manusia selalu diwarnai konflik antara kebenaran dan kebatilan. Setiap zaman memiliki wajah Yazid dan wajah Husein. Pertanyaannya, di pihak mana kita berdiri? Apakah kita menjadi penonton pasif, ataukah kita memilih untuk ikut menyuarakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat? Karbala menantang kita untuk tidak netral, karena netralitas di hadapan tirani adalah bentuk kolaborasi dengan kebatilan. Teriakan Husein di Karbala memaksa kita untuk merenung: apakah kita masih memiliki keberanian moral untuk berkata tidak?
Penulis: Suud Sarim Karimullah