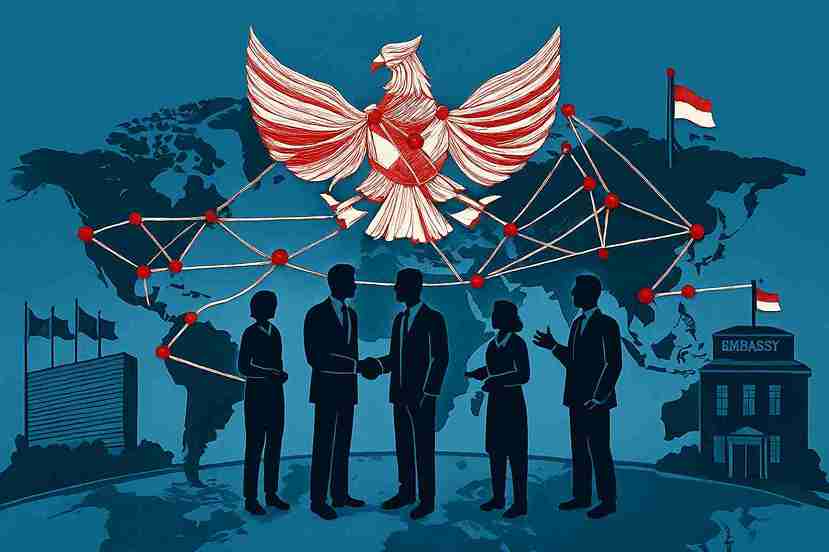Semangat Ibrahim dalam tradisi agama samawi tidak hanya dipahami sebagai kisah historis seorang nabi yang menentang penyembahan berhala, melainkan juga sebagai simbol eksistensial dan etis bagi manusia sepanjang zaman. Ibrahim menghadirkan teladan keberanian untuk menantang tatanan mapan yang dianggap suci padahal menindas, serta menegakkan tauhid sebagai prinsip dasar kemerdekaan manusia.
Jika kisah Ibrahim ditafsirkan lebih dalam, ia sejatinya mengajarkan bahwa tugas manusia tidak berhenti pada dimensi ritual keagamaan, tetapi bergerak ke arah praksis sosial untuk menghancurkan berhala dalam berbagai bentuknya dan menghadapi Namrud dalam segala wujudnya.
Kedua metafora itu tidak terbatas pada artefak fisik di masa lampau, melainkan bertransformasi menjadi sistem nilai, struktur kekuasaan, dan kebudayaan yang mengekang martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, pesan ini memiliki relevansi yang mendalam karena bangsa ini sedang berhadapan dengan banyak “berhala” baru yang lahir dari modernitas, kapitalisme global, serta praktik oligarki yang menyerupai wajah Namrud.
Berhala yang dimaksud bukan lagi sekadar patung batu atau kayu yang disembah dengan ritual primitif, melainkan segala bentuk absolutisasi nilai, ideologi, atau materi yang menjadikan manusia kehilangan kebebasan berpikir dan bertindak secara otentik. Konsumerisme yang melahirkan perilaku hedonistik, misalnya, adalah bentuk berhala baru yang menguasai kesadaran kolektif.
Orang dinilai bukan dari integritas atau kontribusi pada kemanusiaan, melainkan dari merek pakaian, kendaraan, atau gawai yang dipakai. Dalam masyarakat Indonesia yang kian urban dan digital, pola konsumsi ini semakin mengekang karena dikukuhkan oleh media sosial yang menciptakan budaya pamer dan kompetisi semu.
Berhala lain hadir dalam bentuk ideologi politik yang dipuja seakan-akan kebenaran tunggal, padahal praktiknya sering kali menindas rakyat. Dalam sejarah Indonesia, kita pernah melihat bagaimana rezim otoriter memanfaatkan narasi besar tentang pembangunan atau keamanan nasional untuk menjustifikasi represi terhadap kebebasan sipil.
Di era demokrasi pun, fenomena politik uang, kultus individu, dan oligarki menunjukkan bahwa berhala masih bercokol kuat. Nama-nama besar elite politik menjadi simbol kekuasaan yang dianggap tak tergoyahkan, sementara aspirasi rakyat tersingkir dari pusat kebijakan.
Semangat Ibrahim mendorong kita untuk meruntuhkan berhala politik semacam ini dengan keberanian menegakkan partisipasi publik, transparansi, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, berhala politik tidak bisa dihancurkan dengan retorika semata, melainkan dengan membangun budaya demokrasi yang kritis, beretika, dan berpihak pada rakyat.
Namrud dalam kisah Ibrahim melambangkan penguasa tiran yang menolak kebenaran dan menindas mereka yang menentang sistemnya. Dalam sejarah panjang manusia, Namrud bisa berwujud raja yang absolut, diktator militer, atau bahkan rezim ekonomi yang mengeksploitasi rakyat demi segelintir elit.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, Namrud dapat menjelma menjadi struktur oligarki ekonomi-politik yang mengendalikan sumber daya alam dan kebijakan publik untuk kepentingan segelintir orang. Contohnya dapat kita lihat pada eksploitasi tambang, penggundulan hutan, serta perampasan tanah yang sering terjadi di berbagai daerah.
Rakyat kecil kerap menjadi korban, sementara keuntungan mengalir ke konglomerat atau investor besar. Menghadapi Namrud semacam ini membutuhkan keberanian moral dan solidaritas kolektif untuk menegakkan keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat adat. Semangat Ibrahim mengajarkan bahwa keberanian melawan tirani bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban etis demi tegaknya kemanusiaan sejati.
Dimensi lain dari semangat Ibrahim adalah kesediaan untuk melakukan dekonstruksi terhadap segala hal yang dianggap “sudah seharusnya” atau taken for granted. Ibrahim berani mempertanyakan keyakinan kolektif masyarakatnya, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan seluruh komunitas dan kekuasaan politik. Dalam konteks Indonesia, sikap kritis seperti ini penting untuk menghadapi warisan kolonialisme dan feodalisme yang masih membekas. Misalnya, praktik diskriminasi berbasis kelas sosial, etnis, atau agama yang masih terjadi menunjukkan bahwa berhala identitas belum sepenuhnya dihancurkan.
Kita sering menyaksikan orang dihakimi bukan karena kapasitasnya, melainkan karena latar belakang primordial yang dilekatkan kepadanya. Semangat Ibrahim menuntut kita untuk menghancurkan berhala identitas ini dengan menegakkan prinsip kesetaraan, bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan hukum dan Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab.
Di era digital, kita cenderung menyanjung teknologi seakan-akan ia mampu menyelesaikan semua masalah manusia. Padahal, teknologi tanpa kendali moral bisa melahirkan bentuk-bentuk penindasan baru, seperti eksploitasi data pribadi, penyebaran hoaks, hingga algoritma yang memperkuat polarisasi sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural, hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak kohesi sosial dan memperlebar jurang perpecahan. Semangat Ibrahim menuntut kita untuk tidak menuhankan teknologi, melainkan menempatkannya sebagai sarana yang tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan.
Semangat Ibrahim juga mengandung dimensi spiritualitas yang membebaskan. Dengan menghancurkan berhala dan melawan Namrud, Ibrahim sejatinya sedang menegakkan tauhid, yakni pengakuan atas keesaan Tuhan yang membebaskan manusia dari segala bentuk ketundukan pada sesama makhluk. Tauhid dalam konteks sosial berarti menolak segala bentuk dehumanisasi, karena hanya Tuhan yang pantas dipuja.
Dalam konteks Indonesia, tafsir sosial dari tauhid ini bisa diwujudkan dalam perjuangan melawan ketidakadilan struktural, korupsi, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Korupsi, misalnya, adalah bentuk nyata dari penyembahan berhala berupa uang dan kekuasaan. Ia merusak fondasi keadilan sosial dan merampas hak rakyat miskin untuk hidup layak. Dengan semangat Ibrahim, bangsa ini harus berani menghadapi Namrud korupsi, tidak hanya dengan hukum positif, tetapi juga dengan perubahan budaya yang menolak kompromi terhadap praktik curang sekecil apapun.
Ibrahim berani berpikir berbeda, bahkan ketika pandangan itu bertentangan dengan arus utama masyarakatnya. Dalam konteks akademik dan intelektual Indonesia, keberanian semacam ini sangat diperlukan untuk membebaskan pendidikan dari dogmatisme dan birokratisasi yang mengekang kreativitas. Pendidikan tidak boleh menjadi berhala yang hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi harus menjadi ruang pembebasan yang melahirkan manusia kritis, kreatif, dan berkarakter.
Kita didorong untuk menciptakan iklim pendidikan yang menantang status quo, membongkar asumsi yang usang, serta menghadirkan ilmu yang berpihak pada kemanusiaan. Hal ini penting agar generasi muda Indonesia tidak menjadi korban dari sistem pendidikan yang hanya melahirkan kepatuhan tanpa daya kritis.
Mengintegrasikan semangat Ibrahim dalam kehidupan bangsa berarti menegakkan kemanusiaan sejati. Kemanusiaan yang sejati bukan sekadar slogan, melainkan praksis hidup yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek. Dalam masyarakat yang semakin kompleks seperti Indonesia, kemanusiaan sejati berarti menolak segala bentuk diskriminasi, menentang eksploitasi, dan menegakkan solidaritas lintas agama, etnis, maupun kelas sosial.
Ketika kita melihat buruh migran diperlakukan tidak adil, ketika perempuan mengalami kekerasan sistemik, atau ketika masyarakat adat kehilangan tanahnya demi investasi, di situlah kita dipanggil untuk menghadirkan semangat Ibrahim untuk menghancurkan berhala egoisme dan melawan Namrud ketidakadilan.
Semangat ini dapat menjadi inspirasi untuk merumuskan kembali arah pembangunan yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegakkan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat demokrasi partisipatif. Bangsa ini membutuhkan keberanian moral untuk menghancurkan berhala-berhala kapitalisme rakus, politik transaksional, dan birokrasi koruptif, serta menghadapi Namrud oligarki yang terus menggerogoti fondasi republik.
Semangat Ibrahim adalah ajakan abadi untuk melakukan kritik, dekonstruksi, dan perlawanan terhadap segala bentuk penyembahan palsu yang menindas martabat manusia. Ia menegaskan bahwa tugas manusia bukan sekadar menyembah secara ritual, melainkan membebaskan diri dan masyarakat dari berhala-berhala sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memperbudak.
Ia juga mengingatkan bahwa Namrud tidak pernah mati, ia selalu hadir dalam wajah-wajah baru yang menguasai zaman. Karena itu, setiap generasi Indonesia dipanggil untuk menghidupkan semangat Ibrahim, agar republik ini tidak kehilangan arah dalam pusaran modernitas dan globalisasi. Hanya dengan keberanian seperti itu, cita-cita kemanusiaan sejati dapat ditegakkan di bumi Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.