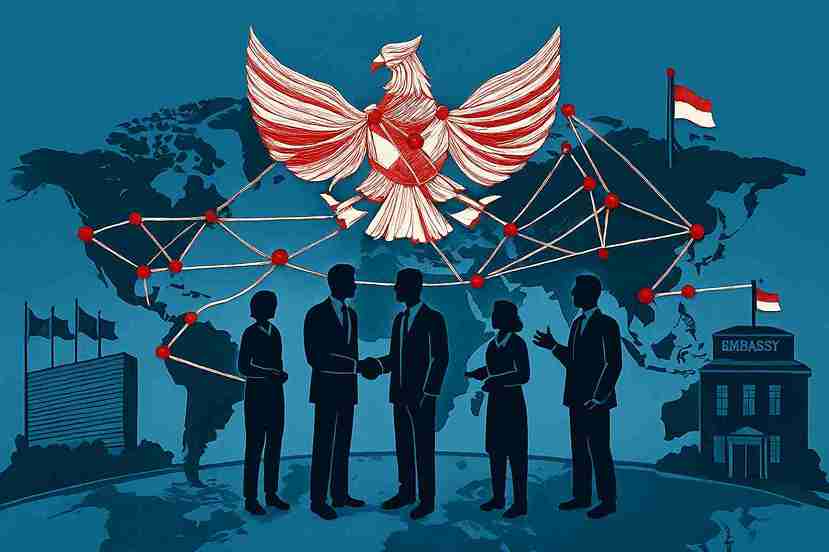Demokrasi yang secara normatif menjanjikan kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum, pada praktiknya sering kali dibajak oleh segelintir elite yang mengendalikan struktur hukum demi kepentingan mereka. Oligarki hukum ini bukan sekadar hadir dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi hukum yang kasat mata, tetapi lebih subtil, sistemik, dan terstruktur.
Ia melekat dalam proses legislasi, seleksi pejabat hukum, interpretasi regulasi, hingga implementasi peradilan, yang seluruhnya diarahkan untuk melanggengkan kepentingan segelintir kelompok dengan kekuatan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, oligarki hukum merupakan wajah tersembunyi dari demokrasi prosedural Indonesia, yang menjadikan hukum sebagai instrumen legitimasi ketidakadilan alih-alih sebagai instrumen koreksi sosial.
Fenomena oligarki hukum dapat dilacak dari cara hukum dibentuk di Indonesia. Secara formal, undang-undang dibentuk melalui mekanisme demokratis antara DPR dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, proses legislasi sering kali dikuasai oleh oligarki politik dan ekonomi yang menanamkan kepentingannya sejak tahap perumusan.
Legislasi tidak lagi murni didasarkan pada aspirasi rakyat, melainkan pada lobi-lobi elite dan transaksi politik yang terjadi di balik layar. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, memperlihatkan bagaimana proses legislasi dapat dipercepat dan dipaksakan tanpa partisipasi publik yang memadai, dengan pasal-pasal yang jelas lebih berpihak kepada kepentingan investasi besar daripada perlindungan buruh atau lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki hukum bekerja bukan hanya melalui korupsi individual, melainkan melalui rekayasa struktural yang membuat hukum sejak lahir sudah bias dan tidak netral. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang deliberasi rakyat berubah menjadi arena kompromi oligarki.
Secara normatif, hukum pidana ditegakkan untuk semua orang tanpa pandang bulu. Namun dalam kenyataan, hukum lebih keras terhadap rakyat kecil dan lebih lunak terhadap elite. Kasus-kasus pencurian kecil kerap dijatuhi hukuman penjara, sementara pelaku korupsi dengan kerugian negara miliaran rupiah dapat menikmati hukuman ringan, fasilitas mewah di penjara, hingga remisi berulang kali.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan berdasarkan prinsip equality before the law, melainkan berdasarkan hierarki kekuasaan. Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, sering kali terjebak dalam relasi patronase dengan elite politik dan ekonomi, sehingga independensi mereka tergadaikan. Akibatnya, hukum menjadi arena negosiasi kepentingan, bukan arena pencarian kebenaran dan keadilan. Fenomena ini semakin meneguhkan adanya oligarki hukum yang beroperasi dalam sistem demokrasi formal.
Oligarki hukum juga terlihat dalam mekanisme seleksi pejabat hukum yang strategis, seperti hakim agung, hakim konstitusi, atau pimpinan lembaga antikorupsi. Proses seleksi yang semestinya menjamin profesionalitas dan integritas sering kali diwarnai pertimbangan politik yang kental. Figur-figur yang kritis terhadap oligarki atau berpotensi independen kerap disingkirkan, sementara mereka yang loyal kepada kekuasaan lebih mudah diakomodasi. Hal ini menunjukkan bagaimana oligarki hukum membentengi dirinya dengan memastikan bahwa aktor-aktor kunci dalam sistem hukum adalah mereka yang dapat dikendalikan atau setidaknya tidak mengganggu status quo.
Mekanisme demokratis yang secara formal ada, seperti uji kelayakan di DPR, justru menjadi pintu masuk bagi dominasi oligarki. Demokrasi prosedural yang diidealkan sebagai kontrol publik atas kekuasaan berubah menjadi filter bagi oligarki untuk melanggengkan hegemoni mereka dalam ranah hukum.
Fenomena oligarki hukum semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ekonomi politik Indonesia. Demokrasi elektoral yang mahal menciptakan ketergantungan partai politik dan kandidat pada sumber daya ekonomi besar. Para oligark ekonomi yang memiliki modal besar menanamkan investasi politik pada kandidat atau partai, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan akses serta pengaruh dalam proses legislasi dan penegakan hukum.
Dalam konteks ini, hukum tidak lagi diproduksi berdasarkan kepentingan publik, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi dan memperluas kepentingan oligark. Perizinan usaha, regulasi investasi, hingga kebijakan sumber daya alam sering kali dirancang untuk menguntungkan korporasi besar, meski dengan mengorbankan masyarakat lokal atau lingkungan hidup. Hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan ekonomi justru dipakai untuk memperkuat dominasi ekonomi segelintir orang.
Demokrasi Indonesia kerap menggunakan jargon supremasi hukum untuk menunjukkan legitimasi, namun dalam praktiknya supremasi hukum hanyalah façade yang menutupi dominasi oligarki. Hukum sering digunakan untuk menyerang lawan politik, sementara kawan politik dilindungi. Selektivitas ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum, karena hukum dipersepsikan sebagai instrumen politik semata.
Di sisi lain, jargon tentang partisipasi publik dalam legislasi sering kali hanya formalitas, di mana aspirasi masyarakat didengar tetapi tidak pernah sungguh-sungguh diakomodasi. Retorika hukum ini menciptakan ilusi demokrasi yang sehat, padahal yang bekerja di bawah permukaannya adalah oligarki hukum yang kokoh.
Kehadiran oligarki hukum dalam negara demokrasi Indonesia juga menimbulkan implikasi serius terhadap hak asasi manusia. Kelompok minoritas, baik etnis, agama, maupun gender, sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Alih-alih melindungi, hukum kerap menjadi alat untuk membatasi ekspresi atau memperkuat dominasi kelompok mayoritas.
Kasus diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas yang ditoleransi bahkan dilegitimasi oleh aturan administratif adalah contoh nyata bagaimana hukum menjadi instrumen eksklusi. Oligarki hukum bekerja dengan cara mengatur akses terhadap hak, sehingga hanya kelompok dominan atau yang berafiliasi dengan oligarki yang menikmati perlindungan penuh. Demokrasi yang seharusnya memperluas hak justru dikooptasi oleh oligarki untuk mempersempitnya.
Dimensi lain yang menunjukkan menguatnya oligarki hukum adalah lemahnya lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Mahkamah Konstitusi, yang semestinya berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, tidak jarang mengeluarkan putusan yang justru dipertanyakan independensinya karena selaras dengan kepentingan penguasa.
Hal serupa juga terjadi pada lembaga antikorupsi yang mengalami pelemahan melalui perubahan regulasi yang jelas-jelas diarahkan untuk mengendalikan independensinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa oligarki hukum tidak hanya bekerja di ranah legislasi atau eksekutif, tetapi juga telah menyusup hingga ke ranah yudikatif.
Dalam konteks sejarah, oligarki hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai kelanjutan dari pola patrimonialisme dan feodalisme yang bertransformasi dalam balutan demokrasi modern. Sejak era Orde Baru, hukum telah lama digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan otoriter.
Reformasi 1998 memang membuka ruang demokratisasi, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan ruang baru bagi oligarki untuk bermanuver. Kebebasan politik pasca-Reformasi justru dimanfaatkan oleh elite ekonomi dan politik untuk memperluas jejaring kekuasaan mereka melalui institusi hukum. Demokrasi elektoral yang mahal menjadi pintu masuk utama, sementara sistem hukum yang rapuh menjadi lahan subur bagi oligarki untuk menanamkan pengaruh.
Membicarakan oligarki hukum dalam demokrasi Indonesia berarti juga mempertanyakan makna substantif dari demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi hanya dipahami sebagai prosedur elektoral lima tahunan, maka oligarki hukum akan terus berkuasa, karena mereka dapat dengan mudah membeli prosedur tersebut melalui kekuatan modal. Namun jika demokrasi dipahami sebagai kedaulatan rakyat dalam arti substantif, maka oligarki hukum adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.
Pertanyaannya, apakah institusi hukum Indonesia mampu membebaskan diri dari cengkeraman oligarki? Ataukah hukum akan terus menjadi instrumen legitimasi oligarki yang semakin mengakar? Tantangan terbesar bagi demokrasi Indonesia adalah bagaimana membongkar struktur oligarki hukum ini, bukan hanya pada level individu pelaku, tetapi pada level sistemik yang melibatkan hubungan antara politik, ekonomi, dan hukum.
Meski demikian, tidak berarti bahwa oligarki hukum tidak dapat dilawan. Gerakan masyarakat sipil, akademisi kritis, media independen, dan organisasi non-pemerintah telah berkali-kali menantang hegemoni oligarki hukum. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, aksi protes terhadap legislasi bermasalah, hingga advokasi internasional menunjukkan bahwa masih ada ruang perlawanan terhadap oligarki. Namun, ruang perlawanan ini sering kali terbatas oleh struktur kekuasaan yang timpang.
Tanpa adanya reformasi mendasar dalam sistem politik dan ekonomi, hukum akan terus menjadi arena dominasi oligarki. Oleh karena itu, pertarungan melawan oligarki hukum bukan hanya pertarungan hukum, tetapi juga pertarungan politik dan sosial yang lebih luas. Hukum harus direbut kembali dari cengkeraman oligarki agar ia dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.
Oligarki hukum di negara demokrasi Indonesia adalah kenyataan pahit yang menyingkap keterbatasan demokrasi prosedural. Demokrasi yang seharusnya menegakkan kedaulatan rakyat justru terkooptasi oleh oligarki yang menggunakan hukum sebagai perisai kekuasaan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi tanpa keadilan hukum hanyalah kosmetik, dan hukum tanpa independensi hanyalah alat oligarki. Untuk membongkar oligarki hukum, diperlukan keberanian kolektif untuk mereformasi sistem legislasi, memperkuat independensi peradilan, membatasi biaya politik, serta memperluas partisipasi publik dalam setiap proses hukum.
Tanpa itu semua, hukum akan terus menjadi milik segelintir elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dalam demokrasi yang seharusnya mereka miliki. Inilah dilema terbesar Indonesia hari ini: apakah kita berani melawan oligarki hukum, ataukah kita akan menerima demokrasi yang hanya sekadar nama tanpa substansi? Pertanyaan ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa, karena tanpa hukum yang bebas dari oligarki, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi panggung ilusi di mana rakyat percaya berdaulat, padahal sejatinya kekuasaan berada di tangan segelintir elite yang mengendalikan segalanya.
Penulis: Suud Sarim Karimullah