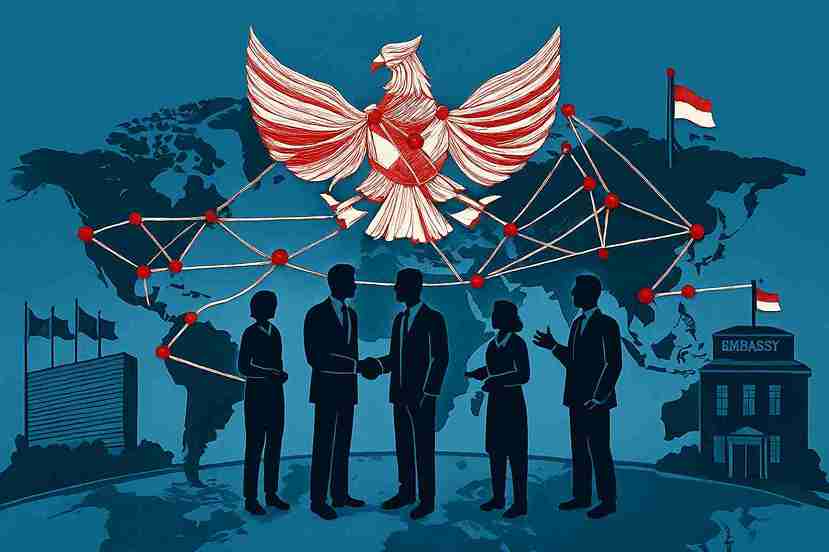Toleransi merupakan salah satu warisan agung peradaban Islam yang relevansinya tidak pernah pudar sepanjang sejarah, bahkan semakin terasa urgensinya di tengah pergulatan global dewasa ini. Kehadiran Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak hanya bermakna bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, karena inti ajarannya menegaskan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.
Toleransi dalam tradisi Islam bukan sekadar sikap permisif atau kompromi dangkal terhadap perbedaan, melainkan landasan filosofis dan praksis dalam membangun peradaban yang berkeadilan, harmonis, dan berkeadaban. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bahwa toleransi tidak pernah dilepaskan dari nilai-nilai tauhid dan moralitas universal, sehingga mampu mengubah masyarakat jahiliyah yang ditandai oleh fanatisme suku, diskriminasi, dan kekerasan, menjadi masyarakat madani yang menempatkan pluralitas sebagai bagian dari kekuatan sosial.
Konsep toleransi dalam Islam memiliki dimensi multidisipliner. Ia dapat dibaca dari sudut pandang teologis, sosial, politik, bahkan epistemologis. Dari sisi teologi, Al-Qur’an secara konsisten mengakui keberadaan perbedaan agama dan budaya sebagai sunnatullah, sebuah keniscayaan yang tidak dimaksudkan untuk dihapus, melainkan dikelola dengan sikap saling menghormati.
Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling meniadakan. Ayat ini tidak hanya menolak homogenitas sebagai cita-cita, melainkan menjadikan perbedaan sebagai modal peradaban.
Dalam perspektif sosial, ajaran toleransi diwujudkan dalam relasi antarumat beragama, sikap terhadap kelompok minoritas, serta penerimaan terhadap keragaman tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara dalam ranah politik, toleransi mewujud dalam sistem pemerintahan yang inklusif sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, yang diakui sebagai salah satu dokumen politik paling progresif dalam sejarah peradaban dunia.
Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah, beliau menghadapi realitas sosial yang sangat majemuk: kaum Muhajirin dari Mekah, kaum Anshar penduduk asli Madinah, serta komunitas Yahudi yang telah lama menetap di sana. Alih-alih menyingkirkan perbedaan itu, Nabi justru membangun sebuah kontrak sosial yang menjamin kebebasan beragama, kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlindungan kolektif terhadap ancaman eksternal.
Piagam Madinah menjadi bukti nyata bagaimana Islam menjadikan toleransi sebagai pilar politik dan sosial yang berorientasi pada keadilan. Melalui piagam tersebut, Islam tidak hanya menawarkan retorika moral, tetapi menghadirkan kerangka institusional yang memastikan perbedaan tidak menjadi sumber konflik destruktif, melainkan bagian dari harmoni yang konstruktif. Dalam hal ini, toleransi tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan produktif, sebab ia menuntut adanya pengakuan, penghormatan, serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai.
Sejarah peradaban Islam pada masa keemasan juga mencatat bagaimana toleransi menjadi instrumen penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di Baghdad pada era Abbasiyah, misalnya, lembaga Bayt al-Hikmah menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Proses ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterbukaan intelektual dan toleransi epistemik terhadap pemikiran di luar tradisi Islam.
Ulama dan ilmuwan Muslim tidak memandang ilmu pengetahuan asing sebagai ancaman terhadap iman, tetapi justru sebagai kekayaan yang dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd adalah tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa toleransi terhadap keragaman epistemologi justru memperkaya khazanah peradaban Islam, menjadikannya sebagai pusat kebangkitan intelektual dunia pada masa itu. Hal yang sama terjadi di Andalusia, sebab interaksi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi melahirkan simbiosis kebudayaan yang memperkaya seni, filsafat, arsitektur, hingga sains.
Toleransi dalam peradaban Islam juga memiliki dimensi ekonomi. Prinsip keadilan distributif yang diajarkan Islam menolak segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf bukan hanya mekanisme spiritual, melainkan instrumen sosial untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bahwa dalam urusan ekonomi sekalipun, toleransi bermakna sebagai penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dalam praktik perdagangan, beliau menekankan kejujuran, transparansi, dan larangan monopoli yang merugikan pihak lemah. Namun, toleransi dalam Islam tidaklah berarti relativisme tanpa batas.
Islam tetap menegaskan prinsip kebenaran yang bersumber dari tauhid, tetapi kebenaran tersebut tidak dipaksakan kepada orang lain. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, karena kebenaran telah jelas berbeda dari kesesatan. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa toleransi Islam tidak lahir dari kelemahan, tetapi dari keyakinan yang kuat terhadap kebenaran. Justru karena Islam meyakini kebenaran, maka ia berani memberikan ruang kebebasan kepada orang lain untuk memilih jalan hidupnya.
Dalam konteks modern, warisan toleransi Islam ini menghadapi tantangan serius. Globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi komunikasi telah membuat dunia semakin terbuka, tetapi pada saat yang sama juga memperbesar potensi konflik identitas. Fenomena islamofobia di Barat dan radikalisme di sebagian kalangan umat Islam menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami esensi toleransi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Islamofobia lahir dari stereotip negatif yang melihat Islam sebagai agama intoleran dan kekerasan, padahal sejarah membuktikan sebaliknya. Sementara radikalisme lahir dari tafsir sempit terhadap ajaran Islam yang mengabaikan dimensi historis dan kontekstual dari nilai-nilai toleransi. Kedua fenomena ini sama-sama berbahaya karena sama-sama mereduksi Islam dari hakikatnya sebagai agama rahmat bagi semesta alam.
Secara epistemologis, toleransi dapat menjadi jembatan antara tradisi Islam dengan tradisi intelektual modern. Di tengah polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme, Islam dapat menghadirkan paradigma alternatif yang tidak meniadakan iman maupun rasionalitas. Toleransi dalam berpikir berarti membuka diri terhadap kritik, dialog, dan sintesis gagasan tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai dasar.
Tradisi ijtihad dalam Islam sesungguhnya merupakan manifestasi toleransi intelektual, karena mengakui adanya ruang perbedaan pendapat dalam memahami teks wahyu. Keberagaman mazhab fikih dan pemikiran teologi dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus melahirkan perpecahan, melainkan bisa menjadi ruang dialektika yang memperkaya. Jika warisan ini dihidupkan kembali, maka umat Islam dapat tampil sebagai teladan peradaban yang mampu menyatukan iman dan akal, tradisi dan modernitas.
Penulis: Suud Sarim Karimullah