
Mencari keadilan substantif di tengah formalisme hukum adalah sebuah paradoks yang selalu menjadi perdebatan panjang dalam filsafat hukum maupun praktik peradilan. Hukum yang secara ideal diciptakan untuk menegakkan keadilan, sering kali justru terjebak dalam ritual prosedural yang kaku dan tekstual, sehingga kehilangan daya transformatifnya.
Formalisme hukum, yang berakar pada positivisme, menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, moralitas, atau rasa keadilan masyarakat. Dalam pandangan ini, hakim dipandang tidak lebih dari corong undang-undang yang hanya menjalankan teks, bukan pencari keadilan. Akan tetapi, realitas sosial selalu lebih kompleks daripada teks hukum, sehingga formalisme justru kerap menimbulkan ketidakadilan.
Di titik inilah pencarian keadilan substantif menemukan urgensinya, yakni bagaimana menjadikan hukum bukan hanya sekadar kepastian formal, tetapi juga alat untuk mencapai kebenaran yang hidup dalam masyarakat.
Formalisme hukum sering kali digambarkan sebagai upaya menjaga kepastian hukum, yang dianggap sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Kepastian hukum memang penting, sebab tanpa kepastian, hukum bisa kehilangan otoritasnya dan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian yang membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Namun, persoalan muncul ketika kepastian hukum dipuja sedemikian rupa sehingga mengorbankan keadilan substantif.
Dalam konteks ini, hukum berubah menjadi ritual administrasi yang mengutamakan prosedur di atas substansi. Banyak kasus di pengadilan memperlihatkan bagaimana hakim terikat pada pasal-pasal yang rigid, padahal jika menggunakan nurani dan kepekaan sosial, putusan seharusnya bisa lebih adil. Formalisme menutup ruang interpretasi kritis, menjadikan hukum kering, dan mengalienasi masyarakat dari rasa keadilan yang mereka harapkan.
Keadilan substantif menuntut hukum untuk lebih dari sekadar kepastian. Ia menuntut agar hukum menjadi alat emansipasi, yang sanggup menjawab kompleksitas persoalan manusia dalam masyarakat. Keadilan substantif memandang bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kearifan lokal.
Dalam konteks Indonesia, keadilan substantif berarti hukum harus berakar pada Pancasila sebagai cita hukum, yang menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan tertinggi. Artinya, ketika terjadi ketegangan antara kepastian formal dengan keadilan substantif, maka hukum seharusnya lebih berpihak pada keadilan substantif.
Namun, dalam praktiknya, pergeseran orientasi ini tidak mudah, karena formalisme telah mengakar dalam struktur, budaya, dan mentalitas aparat hukum. Peradilan cenderung mengutamakan aspek prosedural, seperti bukti tertulis, prosedur formil, dan batasan teknis, sementara kebenaran materiel dan rasa keadilan masyarakat sering kali dikesampingkan.
Pencarian keadilan substantif di tengah formalisme hukum sering kali diperhadapkan dengan dilema yang nyata. Misalnya, dalam kasus pidana, hakim sering dihadapkan pada situasi di mana pelanggaran prosedural kecil justru berimplikasi besar pada nasib terdakwa.
Kesalahan administrasi dalam proses penyidikan bisa membuat bukti yang sebenarnya valid dianggap cacat, sehingga terdakwa bisa bebas, meskipun secara substantif terbukti bersalah. Di sisi lain, formalisme juga bisa membuat terdakwa yang seharusnya tidak bersalah terjebak dalam putusan bersalah hanya karena tidak mampu memenuhi prosedur pembuktian yang rumit.
Dalam kedua kasus itu, formalisme hukum jelas menghambat tercapainya keadilan substantif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah hukum dibuat untuk menegakkan keadilan, ataukah keadilan harus dikorbankan demi kesucian prosedur?
Di balik dilema itu, terdapat masalah struktural yang lebih dalam. Sistem hukum Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa kontinental, yang menekankan kodifikasi, kepastian, dan legalisme. Tradisi ini melahirkan birokrasi hukum yang menempatkan teks undang-undang di atas segala-galanya.
Hakim, jaksa, dan advokat dididik untuk berpikir formalistik, bukan kritis. Pendidikan hukum di perguruan tinggi lebih banyak mengajarkan hafalan pasal-pasal daripada pemahaman filosofis tentang tujuan hukum. Akibatnya, para praktisi hukum cenderung terjebak dalam mentalitas “apa bunyi pasalnya” daripada “apa tujuan hukumnya”. Mentalitas ini melanggengkan formalisme hukum, sekaligus menghambat lahirnya putusan-putusan progresif yang berpihak pada keadilan substantif.
Keadilan substantif tidak dapat dicapai tanpa keberanian untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif. Hakim sebagai aktor sentral dalam peradilan harus berani keluar dari kungkungan formalisme. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang, tetapi harus menjadi penafsir yang kritis dan peka terhadap konteks sosial.
Sejarah hukum menunjukkan bahwa putusan-putusan progresif sering kali lahir ketika hakim berani melampaui teks dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi Indonesia, misalnya, dalam beberapa putusannya berhasil menggeser orientasi dari sekadar kepastian formal ke arah keadilan substantif, seperti dalam putusan terkait hutan adat.
Putusan semacam ini menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat perubahan sosial, asalkan ada keberanian untuk melawan formalisme yang kaku. Namun, pencarian keadilan substantif juga tidak boleh jatuh pada jebakan relativisme yang mengabaikan kepastian hukum. Tanpa kepastian, hukum bisa berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah keseimbangan dialektis antara kepastian formal dan keadilan substantif.
Formalisme hukum diperlukan sebagai batas agar hukum tidak ditafsirkan secara liar, tetapi keadilan substantif juga harus menjadi tujuan yang membimbing formalisme itu. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utama hukum tetaplah keadilan substantif. Dialektika ini menuntut kemampuan intelektual, moralitas, dan sensitivitas sosial dari para penegak hukum. Tanpa ketiga hal itu, hukum akan terus terjebak dalam formalisme yang steril dan jauh dari aspirasi rakyat.
Keadilan substantif juga menuntut perubahan paradigma dalam pembuatan undang-undang. Legislasi tidak boleh hanya menjadi produk kompromi politik elite, tetapi harus benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat. Proses legislasi yang partisipatif akan memperkuat keadilan substantif, karena hukum yang lahir dari aspirasi rakyat akan lebih adil secara sosial.
Sayangnya, banyak undang-undang di Indonesia justru disusun dengan orientasi kepentingan ekonomi dan politik, bukan keadilan rakyat. Formalisme kemudian memperparah keadaan, karena aparat penegak hukum dipaksa menegakkan undang-undang yang substansinya sudah tidak adil.
Hukum yang substantif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan moralitas masyarakat. Indonesia dengan keragamannya memiliki kekayaan kearifan lokal yang bisa menjadi sumber nilai keadilan. Namun, formalisme hukum sering kali menyingkirkan nilai-nilai lokal ini, karena hanya mengakui hukum tertulis yang disahkan negara.
Keadilan substantif juga berarti mengakui pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum agama, dan nilai-nilai sosial mendapat ruang untuk hidup berdampingan dengan hukum nasional. Pengakuan pluralisme hukum bukan berarti menolak unifikasi, tetapi justru memperkaya sistem hukum nasional dengan keberagaman nilai keadilan yang hidup di masyarakat.
Dalam perspektif filosofis, pencarian keadilan substantif di tengah formalisme hukum menegaskan kembali perdebatan klasik antara positivisme hukum dan aliran hukum alam. Positivisme, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan terpisah dari moral.
Sebaliknya, aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum harus selaras dengan nilai keadilan universal. Di tengah perdebatan ini, keadilan substantif hadir sebagai kritik terhadap positivisme yang kaku. Ia menuntut agar hukum tidak hanya dipandang sebagai teks, tetapi juga sebagai praksis sosial yang berhubungan dengan keadilan manusia.
Jika dicermati, pencarian keadilan substantif di tengah formalisme hukum adalah cermin dari krisis legitimasi hukum di masyarakat. Banyak rakyat yang merasa hukum tidak berpihak kepada mereka, tetapi hanya menjadi alat penguasa dan pemodal. Hukum kehilangan wibawanya karena gagal menghadirkan keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Demonstrasi, konflik agraria, kriminalisasi aktivis, dan berbagai bentuk ketidakpuasan sosial adalah tanda-tanda bahwa masyarakat sedang menuntut keadilan substantif. Jika hukum terus terjebak dalam formalisme yang kaku, maka jurang antara hukum dan masyarakat akan semakin lebar, dan legitimasi hukum akan runtuh. Oleh karena itu, pencarian keadilan substantif bukan hanya agenda akademik, tetapi juga agenda politik dan moral bangsa.
Pencarian keadilan substantif di tengah formalisme hukum adalah perjuangan yang panjang dan berliku. Ia menuntut keberanian intelektual, integritas moral, dan komitmen politik dari semua aktor hukum, mulai dari legislator, hakim, jaksa, advokat, hingga akademisi. Ia juga menuntut partisipasi aktif masyarakat untuk terus mengawal agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan yang menindas.
Pencarian ini adalah upaya untuk mengembalikan hukum pada hakikatnya, yaitu sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial, bukan sekadar prosedur kosong. Dalam konteks Indonesia, keadilan substantif harus berakar pada Pancasila, konstitusi, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi menara gading yang jauh dari rakyat, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama tempat keadilan substantif diwujudkan.




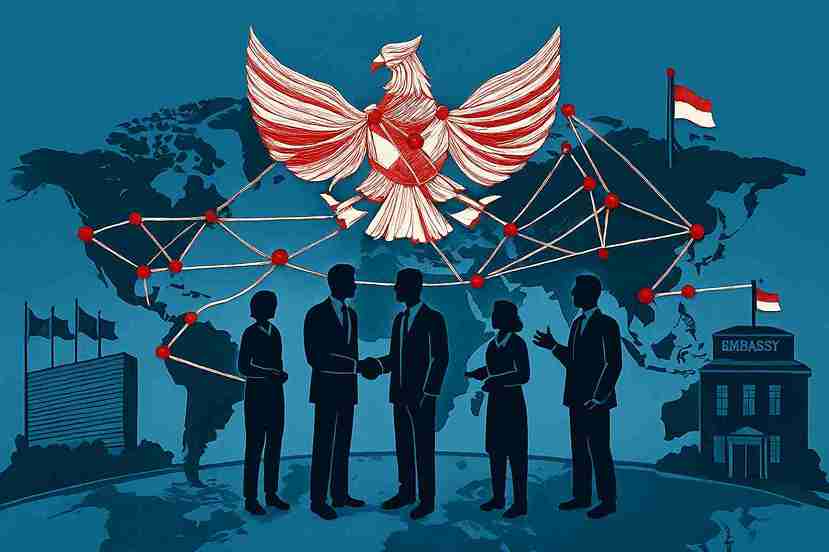

These are genuinely impressive ideas in regarding blogging.
You have touched some nice factors here. Any way
keep up wrinting.
Thank you so much! I really appreciate your kind words 😊 I’ll definitely keep writing and sharing more soon!