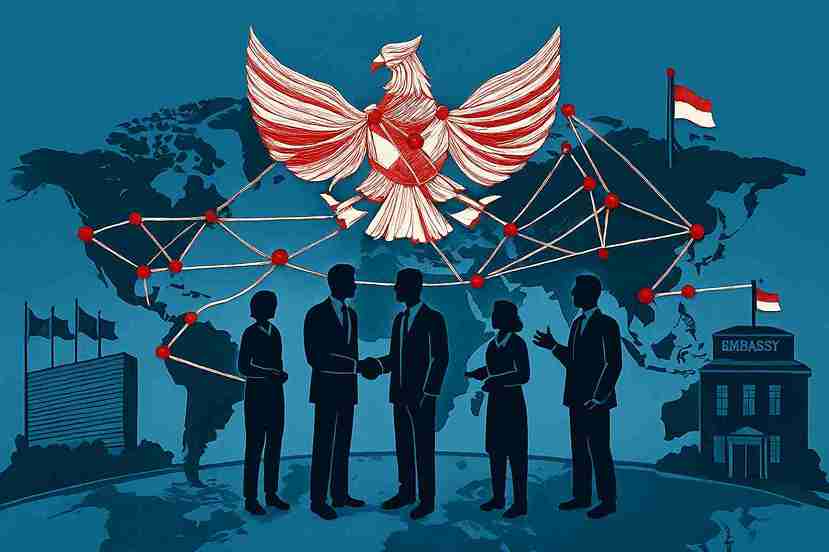Ketika Imam Husein menolak diam di hadapan tirani, ia tidak sedang melakukan tindakan spontan yang lahir dari keberanian sesaat, melainkan menjalankan sebuah proyek moral yang berakar dalam pada nilai-nilai profetik. Keputusan itu tidak bisa dipahami hanya sebagai sikap politik, melainkan sebagai gerakan spiritual yang menjelma ke dalam arena sejarah.
Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak tunduk pada perintah Yazid bin Muawiyah untuk memberikan baiat, sebab ia melihat dengan jelas bahwa rezim yang berdiri di Damaskus tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Islam, melainkan menjadikan agama sebagai legitimasi bagi kekuasaan dinasti. Diam dalam konteks itu bukanlah pilihan netral, melainkan bentuk persetujuan terselubung terhadap penyimpangan. Maka, ketika Husein menolak diam, ia sejatinya menegaskan bahwa dalam menghadapi kebatilan, keheningan adalah pengkhianatan, dan keberanian bersuara adalah kewajiban moral.
Tragedi Karbala tidak akan pernah dimengerti sepenuhnya bila dilihat hanya dari dimensi politik yang dangkal. Husein bukanlah seorang pemberontak yang haus kekuasaan, melainkan seorang pewaris moralitas kenabian yang melihat bagaimana agama dipelintir demi melanggengkan status quo. Yazid, yang naik tahta melalui mekanisme pewarisan dinasti, menuntut pengakuan simbolik dari tokoh-tokoh penting umat Islam agar pemerintahannya sah secara moral.
Dari semua tokoh itu, Husein adalah yang paling penting karena ia cucu Nabi, simbol yang memiliki legitimasi spiritual tak tertandingi. Apabila Husein diam, maka diamnya akan ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan, dan pengakuan itu akan membungkam kritik terhadap sistem yang sedang korup. Karena itu, penolakannya bukan sekadar sikap pribadi, melainkan tindakan untuk menjaga agar kebenaran tidak ditelan oleh narasi kekuasaan.
Penolakan Husein terhadap diam dapat dipahami sebagai bentuk resistensi eksistensial. Ia menolak menjadi subjek yang tunduk pada struktur kuasa yang korup, dan memilih untuk menegaskan kebebasan moralnya meskipun konsekuensinya adalah kematian. Tindakan ini menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari penderitaan, tetapi bebas dari kompromi dengan kebatilan.
Dalam kerangka eksistensialisme, keberanian Husein mengingatkan bahwa hidup hanya bermakna jika dijalani dengan kesetiaan pada nilai. Tanpa itu, hidup hanyalah rangkaian kompromi yang menggerogoti kemanusiaan. Karena itu, Karbala bukan hanya tragedi religius, tetapi juga peristiwa filsafat yang menyingkap makna kebebasan, keberanian, dan kesetiaan pada nilai.
Penolakan Husein terhadap diam adalah jihad dalam arti yang paling esensial. Jihad tidak semata pertempuran fisik, melainkan perjuangan mempertahankan integritas iman di tengah tekanan duniawi. Dengan menolak tunduk pada Yazid, Husein memperlihatkan bahwa ibadah sejati adalah keberanian moral, bukan sekadar ritual lahiriah.
Ia menolak menjadikan agama sebagai topeng kekuasaan, dan dengan itu ia mengembalikan agama pada posisinya yang asli: sebagai jalan menuju keadilan. Karbala adalah khutbah hidup, sebuah dakwah yang tidak disampaikan melalui kata-kata, tetapi melalui darah dan pengorbanan.
Penolakan Husein untuk diam juga menegaskan bahwa keadilan membutuhkan harga mahal. Ia memperlihatkan bahwa kebenaran tidak akan pernah menang murah, dan bahwa setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Husein rela mengorbankan nyawa, keluarganya, dan kenyamanan duniawi demi menjaga nilai-nilai moral.
Dari sini kita belajar bahwa setiap masyarakat yang ingin menegakkan keadilan harus siap membayar harga. Tidak ada keadilan yang lahir dari kompromi dengan tirani, dan tidak ada kebebasan yang tumbuh dari keheningan. Darah Husein adalah pengingat bahwa keadilan hanya hidup ketika ada orang yang berani menolak diam, bahkan ketika konsekuensinya adalah kematian.
Penolakan Imam Husein terhadap diam bukanlah sekadar episode sejarah, tetapi sebuah pelajaran yang terus relevan. Ia menantang kita untuk menolak netralitas palsu, untuk menolak kompromi yang menggadaikan nilai, dan untuk berani berkata tidak pada tirani. Ia mengingatkan bahwa diam adalah bentuk partisipasi dalam kezaliman, dan bahwa keberanian untuk bersuara adalah bentuk tertinggi dari iman. Maka, selama manusia masih bergulat dengan ketidakadilan, selama tirani masih bercokol dalam berbagai wajahnya, spirit Karbala akan terus hidup, memanggil kita semua untuk menolak diam dan memilih jalan kebenaran meski harus membayar dengan harga yang paling mahal.
Penulis: Suud Sarim Karimullah