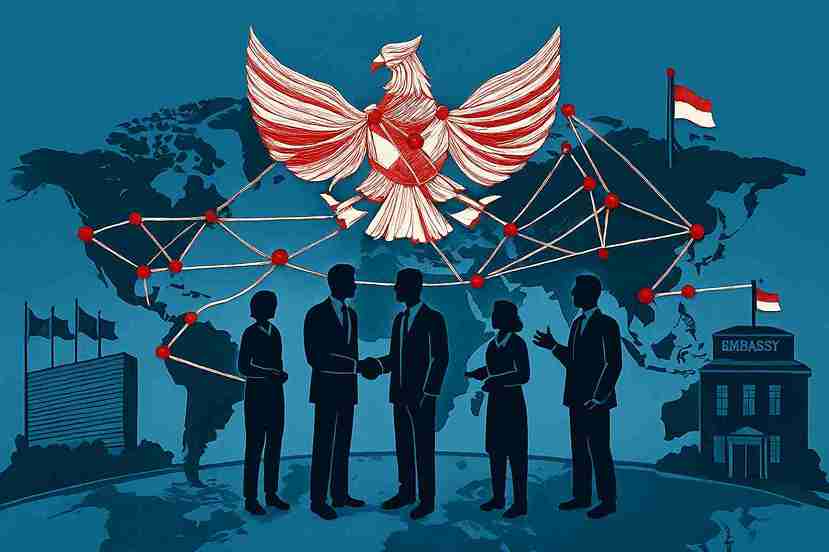Keadilan politik dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tonggak terpenting yang membedakan Islam dari tradisi politik otoritarian dan oligarkis pada zamannya. Kehadiran Rasulullah tidak hanya membawa risalah spiritual yang membimbing manusia menuju tauhid, tetapi juga menghadirkan model pemerintahan yang menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dan musyawarah sebagai mekanisme partisipatif.
Keadilan dalam bingkai demokrasi yang dipraktikkan Nabi bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas politik yang nyata, yang diimplementasikan dalam tatanan sosial Madinah. Hal ini menjadikan Rasulullah bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang negarawan besar yang berhasil memadukan spiritualitas, etika, dan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban. Jika demokrasi modern kerap dipahami sebatas sistem representatif dengan mekanisme elektoral, maka Nabi Muhammad menghadirkan demokrasi yang lebih substansial, yang bertumpu pada nilai keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Konteks politik Arab pra-Islam ditandai oleh budaya jahiliyah yang berakar pada struktur kesukuan yang hierarkis dan feodal. Kekuasaan dikuasai oleh elite kabilah yang mempertahankan otoritas melalui patronase, perang, dan dominasi ekonomi. Tidak ada sistem hukum yang jelas, tidak ada keadilan yang berlaku universal, dan masyarakat hidup dalam logika “siapa yang kuat dialah yang berkuasa.” Dalam atmosfer sosial semacam ini, kehadiran Nabi Muhammad menghadirkan perubahan radikal.
Dengan Piagam Madinah sebagai instrumen konstitusional, Rasulullah menegakkan prinsip keadilan politik yang melintasi batas-batas suku, agama, dan kelas sosial. Piagam itu menegaskan bahwa seluruh warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu komunitas politik yang setara hak dan kewajibannya. Dokumen ini mencerminkan demokrasi dalam arti substantif: kesetaraan hukum, partisipasi kolektif, dan kontrak sosial yang berlandaskan keadilan.
Keadilan politik Rasulullah juga terwujud dalam praktik musyawarah yang konsisten. Al-Qur’an mengabadikan musyawarah sebagai salah satu ciri orang beriman, bahwa “urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” (Asy-Syura: 38). Ayat ini bukan sekadar nasihat etis, tetapi menjadi fondasi normatif bagi pengambilan keputusan politik. Nabi tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa absolut, melainkan pemimpin yang membuka ruang deliberasi.
Dalam Perang Uhud, misalnya, beliau lebih condong bertahan di dalam kota, namun ketika mayoritas sahabat memilih keluar menghadapi musuh di medan terbuka, Nabi mengikuti keputusan kolektif meskipun berbeda dengan keinginannya. Peristiwa ini menegaskan bahwa Nabi menjadikan musyawarah bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme nyata dalam menentukan arah kebijakan politik. Inilah esensi demokrasi bahwa kedaulatan dalam pengambilan keputusan tidak dimonopoli oleh satu individu, tetapi dibentuk melalui partisipasi dan konsensus.
Rasulullah juga menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial. Dalam kasus seorang perempuan bangsawan dari Bani Makhzum yang mencuri, ada sebagian elite Quraisy yang mencoba meminta keringanan hukuman. Nabi dengan tegas menolak intervensi semacam itu dan menyatakan bahwa “Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika moral, melainkan prinsip hukum yang menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik atau status sosial.
Dalam dimensi sosial-politik, Nabi Muhammad menegaskan keadilan politik dengan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap kelompok minoritas. Kaum Yahudi di Madinah diberi kebebasan untuk memeluk agama mereka, mengatur urusan internalnya sendiri, dan memiliki hak politik yang sama dalam kontrak sosial Piagam Madinah. Prinsip ini menunjukkan bahwa politik Nabi bersifat demokratis dalam pengertian pluralistik sebab ia tidak meniadakan identitas kelompok, tetapi justru mengakomodasinya dalam kerangka kebersamaan.
Demokrasi tidak berarti menelan perbedaan menjadi satu homogenitas, melainkan membiarkan perbedaan hidup berdampingan dalam ruang keadilan. Dalam konteks itu, Nabi berhasil membangun masyarakat multikultural yang berdiri di atas kesepakatan politik yang adil, bukan pada dominasi mayoritas atau hegemoni kekuasaan.
Aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana Nabi mempraktikkan akuntabilitas politik. Rasulullah membuka ruang bagi sahabat untuk mengoreksi kebijakan beliau. Pada peristiwa Perang Badar, ketika Nabi memilih posisi pasukan, seorang sahabat bernama Hubab bin Mundhir mengusulkan strategi lain yang lebih menguntungkan.
Nabi menerima usulan tersebut tanpa merasa terancam kewibawaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan Nabi, kritik bukanlah ancaman, melainkan kontribusi. Inilah wajah demokrasi dalam Islam sebab pemimpin tidak kebal kritik, dan kebenaran tidak dimonopoli oleh satu orang, bahkan oleh Nabi sekalipun dalam urusan strategi duniawi. Prinsip akuntabilitas ini memperlihatkan bahwa keadilan politik Rasulullah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memberi ruang bagi dinamika bottom-up.
Sebagian kalangan menganggap tidak tepat menyebut Madinah sebagai model demokrasi, karena demokrasi modern lahir dari tradisi Barat dengan fondasi filsafat yang berbeda. Akan tetapi, pandangan ini terlalu sempit jika demokrasi dipahami hanya dalam kerangka elektoral atau sekular.
Madinah menawarkan demokrasi dalam makna substansial dengan pemerintahan berbasis kontrak sosial, musyawarah, kesetaraan hukum, kebebasan beragama, dan keadilan distributif. Bahkan, bisa dikatakan bahwa model politik Nabi lebih progresif daripada banyak sistem monarki absolut atau oligarki yang bertahan berabad-abad setelahnya.
Demokrasi modern sering jatuh pada relativisme moral, sebab keputusan mayoritas dianggap sah meskipun bertentangan dengan keadilan substantif. Dalam pandangan Islam, keputusan politik tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam bukanlah demokrasi tanpa batas, melainkan demokrasi yang dituntun oleh nilai-nilai moral transenden.
Pemimpin dalam Islam bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Adil. Konsep ini memberikan koreksi terhadap demokrasi liberal yang cenderung memutlakkan kedaulatan manusia tanpa ikatan nilai. Demokrasi Islam dalam bingkai keadilan politik Rasulullah justru menawarkan sintesis antara kebebasan manusia dan keterikatan pada kebenaran ilahiah.
Keadilan politik Rasulullah juga bersifat transformatif, karena berhasil mengangkat posisi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Kaum miskin, budak, dan perempuan mendapatkan hak-hak politik dan sosial yang lebih baik dibandingkan era jahiliyah. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, dijadikan muazin utama Nabi, sebuah posisi publik yang strategis.
Perempuan diberi hak untuk terlibat dalam baiat politik, sebagaimana dicatat dalam sejarah ketika mereka membaiat Nabi di Aqabah. Transformasi ini menegaskan bahwa keadilan politik dalam Islam bersifat inklusif, menjangkau semua kelompok tanpa diskriminasi. Hal ini menandingi banyak peradaban lain pada masa itu yang masih menempatkan kelompok-kelompok tertentu sebagai warga kelas dua. Madinah di bawah kepemimpinan Nabi menjadi bukti bahwa demokrasi sejati hanya dapat lahir jika keadilan benar-benar ditegakkan bagi semua lapisan masyarakat.
Demokrasi dalam Islam bukan hanya soal prosedur teknis, melainkan tentang bagaimana menciptakan tata kelola yang mendekatkan manusia kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Konsep ini sangat relevan dalam dunia kontemporer yang sering terjebak pada pragmatisme politik tanpa arah moral. Warisan Nabi menunjukkan bahwa politik dapat sekaligus demokratis, adil, dan spiritual, tanpa harus jatuh pada teokrasi yang menindas kebebasan manusia.
Demokrasi Nabi bukanlah sekadar mitos masa lalu, tetapi sebuah visi peradaban yang menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi politik, musyawarah adalah mekanisme, dan akuntabilitas adalah prinsip. Jika umat Islam mampu menghidupkan kembali semangat ini, maka Islam dapat tampil sebagai kekuatan moral global yang tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga tentang tata dunia yang adil dan demokratis.
Penulis: Suud Sarim Karimullah