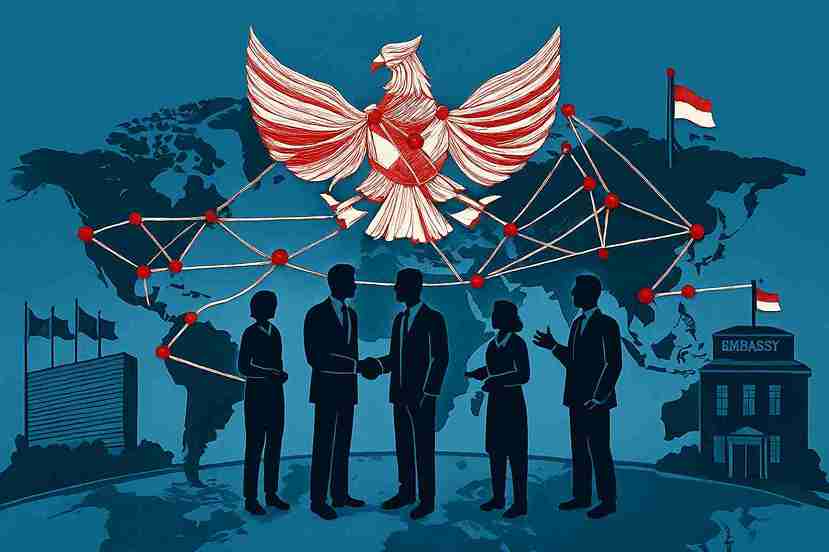Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE, sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa kali revisi, telah menjadi instrumen hukum yang sangat berpengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pada dasarnya berkewajiban untuk menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945.
Namun, kehadiran UU ITE menimbulkan paradoks yang menarik sekaligus provokatif: di satu sisi ia diklaim sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan dari penyalahgunaan teknologi digital, tetapi di sisi lain ia dituding sebagai instrumen represif yang berpotensi membungkam kebebasan berbicara. Pertanyaan apakah UU ITE benar-benar membungkam kebebasan bicara tidak dapat dijawab secara sederhana, karena hal ini menyangkut relasi yang kompleks antara hukum, demokrasi, kekuasaan, serta kultur digital masyarakat Indonesia.
Dalam praktiknya, banyak pasal dalam UU ITE yang dinilai bermasalah karena multitafsir dan rawan disalahgunakan. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, serta Pasal 29 tentang ancaman kekerasan, misalnya, sering dijadikan dasar untuk melaporkan pihak-pihak yang dianggap merugikan kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Pasal-pasal ini memang dimaksudkan untuk menjaga etika komunikasi di ruang digital, tetapi dalam kenyataannya justru sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, baik terhadap individu yang berkuasa, institusi pemerintah, maupun korporasi besar. Banyak kasus menunjukkan bahwa kritik publik yang disampaikan melalui media sosial justru berujung pada pelaporan pidana dengan dalih pencemaran nama baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UU ITE lebih banyak digunakan untuk melindungi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan daripada melindungi kebebasan berekspresi warga biasa.
Fenomena kriminalisasi warganet karena unggahan di media sosial memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus seperti mahasiswa, aktivis, jurnalis, bahkan masyarakat umum yang mengunggah kritik terhadap pejabat publik lalu dijerat dengan UU ITE menjadi bukti konkret bahwa kebebasan berbicara di Indonesia menghadapi ancaman serius.
Perbedaan antara kritik yang sahih sebagai bagian dari demokrasi dan ujaran kebencian yang memang membahayakan harmoni sosial sering kali kabur dalam penerapan hukum. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi arena deliberasi publik dan kontrol sosial justru berubah menjadi ruang penuh ketakutan, di mana masyarakat memilih untuk membungkam diri agar tidak berurusan dengan hukum.
Dalam kerangka demokrasi, kondisi ini tentu kontradiktif. Demokrasi hanya dapat tumbuh sehat jika warga negara bebas menyampaikan pandangan, bahkan kritik keras sekalipun, terhadap penguasa. Tanpa kebebasan ini, mekanisme akuntabilitas akan lumpuh, karena pemerintah tidak lagi mendapat koreksi dari masyarakat.
UU ITE yang digunakan secara represif pada dasarnya memperlemah kualitas demokrasi Indonesia dengan cara mengurangi ruang publik bagi diskursus kritis. Hal ini semakin bermasalah jika kita mengingat bahwa demokrasi Indonesia sendiri masih berusaha memperkuat fondasinya pascareformasi, sehingga instrumen hukum yang ambigu justru akan melanggengkan praktik otoritarianisme terselubung.
Meski demikian, penting untuk memahami bahwa UU ITE tidak bisa dipandang secara sepihak sebagai alat represi semata. Kehadiran regulasi ini pada awalnya memang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merespons perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Penyebaran hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, pornografi daring, penipuan digital, hingga serangan siber nyata adanya dan menimbulkan dampak sosial yang besar. Tanpa instrumen hukum yang jelas, masyarakat akan rentan terhadap kejahatan digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, UU ITE juga memiliki sisi protektif yang tidak bisa diabaikan. Persoalannya adalah keseimbangan: sejauh mana UU ITE melindungi masyarakat dari ancaman nyata di dunia maya, dan sejauh mana ia mengekang kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi?
Salah satu problem utama adalah formulasi pasal-pasal yang terlalu luas dan kabur. Misalnya, frasa “penghinaan” atau “pencemaran nama baik” tidak memiliki batasan yang tegas, sehingga interpretasinya sangat subjektif. Hal ini membuka ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan sesuai dengan kepentingan tertentu. Ketidakjelasan norma hukum inilah yang menciptakan overcriminalization, di mana ekspresi yang seharusnya dilindungi justru dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks inilah muncul kritik bahwa UU ITE lebih banyak digunakan sebagai senjata politik daripada instrumen hukum netral.
Dampak psikologis dari kondisi ini sangat signifikan. Banyak masyarakat menjadi takut untuk bersuara, bahkan dalam isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Aktivis lingkungan, misalnya, kerap menghadapi jeratan UU ITE ketika mengkritik perusahaan tambang yang merusak ekosistem.
Jurnalis independen yang mengangkat kasus korupsi pejabat publik juga tidak jarang dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ketakutan ini menciptakan efek membungkam (chilling effect), di mana masyarakat memilih diam daripada mengambil risiko hukum. Efek ini jauh lebih berbahaya daripada kasus individu, karena ia mengikis budaya demokrasi dan membentuk masyarakat yang apatis terhadap isu publik.
Jika ditelaah lebih dalam, UU ITE juga mencerminkan ketegangan antara dua kepentingan besar dalam tata kelola negara modern: perlindungan terhadap ketertiban umum dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Pemerintah cenderung menekankan aspek ketertiban dengan alasan menjaga stabilitas, sementara masyarakat sipil menuntut ruang ekspresi yang luas sebagai bagian dari hak asasi.
Ketegangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Namun, masalahnya adalah Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi demokrasi, sehingga keberadaan regulasi yang represif lebih berisiko mengembalikan praktik-praktik otoritarian dibanding memperkuat sistem demokratis.
Revisi UU ITE yang dilakukan pada 2016 dan wacana revisi selanjutnya menunjukkan bahwa ada kesadaran atas masalah ini, tetapi perubahan yang dihasilkan belum cukup menjawab kekhawatiran publik. Beberapa pasal yang dianggap bermasalah memang diperhalus, tetapi substansi multitafsir tetap dipertahankan. Bahkan, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menjerat kritik. Ini menunjukkan bahwa problem UU ITE bukan hanya pada teks hukum, tetapi juga pada kultur penegakan hukum dan relasi kekuasaan yang melingkupinya.
Dalam konteks sosial-politik, UU ITE memperlihatkan bagaimana hukum bisa berfungsi ganda: sebagai instrumen regulasi sekaligus instrumen kekuasaan. Ketika digunakan secara adil, ia bisa melindungi masyarakat dari bahaya nyata di ruang digital. Namun ketika digunakan secara selektif, ia menjadi alat kontrol untuk membungkam suara-suara kritis. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia masih rentan dipolitisasi, di mana kepentingan elite bisa mengalahkan prinsip keadilan substantif.
Penting juga untuk dicatat bahwa masyarakat digital Indonesia sendiri sedang berada dalam fase transisi. Ledakan media sosial membawa kebebasan berekspresi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan persoalan serius seperti polarisasi politik, penyebaran ujaran kebencian, dan banjir disinformasi.
Dalam konteks ini, negara memang membutuhkan instrumen hukum untuk menjaga agar ruang digital tidak berubah menjadi arena kekacauan. Namun, regulasi yang represif bukanlah jawabannya, karena justru akan memperburuk polarisasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas, adil, dan seimbang, disertai dengan pendidikan literasi digital yang kuat untuk membangun budaya komunikasi sehat.
Problem UU ITE adalah refleksi dari dilema yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebebasan sipil dengan kebutuhan menjaga ketertiban di era digital. UU ITE bukanlah satu-satunya penyebab berkurangnya kebebasan bicara, tetapi ia menjadi simbol dari kegagalan negara dalam menciptakan regulasi yang adil.
Ke depan, diperlukan reformasi hukum yang lebih radikal untuk menghapus pasal-pasal multitafsir, membatasi ruang kriminalisasi, serta memperkuat mekanisme perlindungan kebebasan berpendapat. Tanpa langkah-langkah itu, UU ITE akan terus menjadi bayangan gelap yang menakut-nakuti warganet dan melemahkan demokrasi Indonesia.